 Oleh Rosita
Mahasiswa FSUI pengikut m.k. Penulisan Populer 1988/89
Bandung, lewat pukul sembilan malam. Kami berempat, Mirta, Marti, Hilman dan saya, sibuk mengaduk-aduk daerah pemukiman di sekitar Dago. Untuk ukuran Bandung, hari sudah terlalu larut, dan juga badan kami sudah capek setelah berjam-jam terguncangguncang di dalam bis yang membawa kami dari Jakarta. Tapi bayangan tempat tidur yang empuk tampaknya masih jauh, karena kami masih harus menemani makhluk cowok satu-satunya di dalam rombongan ini mencari rumah saudaranya untuk menginap. Ironis sekali. Seharusnya, dialah yang mengawal kami, cewek-cewek, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Hilman, yang tingkahnya kadang-kadang sering bikin orang geleng-geleng kepala.
Itu tiga setengah tahun yang lalu, ketika Hilman belum menulis mengenai tokoh yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan remaja: Lupus. Dan semenjak itu, perlahan-lahan Hilman menjadi semakin jauh.
Pertama sekali membaca cerita “Lupus” di majalah Hai, rasanya tidak ada yang terlalu istimewa di situ. Saya memang sudah lama menyukai tulisan Hilman, baik itu artikel, cerita pendek, atau pun cerita bersambung. Buat saya, gaya Hilman bercerita enak dibaca, sebab kata-kata yang dipakainya adalah yang saya jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Saya pikir, ketika itu, serial "Lupus" itu pun biasa-biasa saja. Saya tahu nama Hilman akan sering-sering muncul, tapi paling-paling hanya terbatas di majalah Hai saja. Belakangan terbukti bahwa perkiraan saya meleset total.
Cerita "Lupus" terus mengalir, dimuat setiap minggu di majalah Hai. Sementara itu pula, acara jalan-jalan dengan Hilman bersama teman-teman lain yang suka menamakan diri The Famous Five, masih berlangsung terus. Hilman memang tipe cowok 'pasrah' yang dengan rela menemani kami, empat cewek, jalan-jalan seharian di Ancol. Dia juga tidak banyak protes ketika saya ajak bergadang di Cibubur buat melihat komet Halley.
Tapi nasib menentukan lain buat Hilman. Cerita-cerita 'Lupus'-nya diterbitkan oleh Gramedia menjadi sebuah buku kecil dengan judul Tangkaplah Daku Kau Kujitak, dan laris bak kacang goreng. Dua minggu setelah dilempar ke pasaran, buku itu harus dicetak ulang, berkali-kali. Sejak itulah tokoh “Lupus” mulai sering Saya jumpai di mana-mana, tapi sejak itu pula Hilman mulai sulit ditemui.
“Lupus,” cowok SMA yang berbadan tinggi-ceking, berambut gondrong dan selalu mengunyah permen karet itu tiba-tiba saja diterima sebagai figur yang digandrungi di kalangan anak-anak SMP dan SMA.
Suatu hari Hilman datang ke rumah saya. Dia membawa beberapa kaos yang bergambar dan bertulisan “Lupus”, dan berpesan agar kaos-kaos itu dibagi-bagikan kepada anggota The Famous Five lainnya untuk dipakai pada acara “Jumpa Lupus”. “Tapi kamu mesti datang, lho. Kalo nggak kaosnya nggak dikasih,” katanya. Saya lihat-lihat, kaosnya lumayan bagus, karena itu saya sanggupi saja untuk datang ke acara itu.
Apa yang saya lihat pada acara “Jumpa Lupus” itu betul-betul di luar dugaan saya, dan sempat membuat saya merinding. Pukul empat sore. Lantai atas toko buku Gramedia di jalan Matraman sudah dipenuhi oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, pelajar SMP dan SMA. Di tengah ruangan, di atas meja yang disusun menjadi panggung, saya lihat Hilman berdiri dengan beberapa orang temannya, yang menampilkan perwujudan tokoh-tokoh di dalam cerita 'Lupus'-nya. Di sekeliling panggung, puluhan remaja mencoba menyerbu ke panggung.
Saya hampir tidak percaya bahwa sosok yang dielu-elukan gerombolan remaja itu adalah Hilman. Hilman yang malam tadi mengantarkan kaos ke rumah, Hilman yang pasrah dan telaten menemani kami, Hilman yang ....
Serbuan penggemar “Lupus” kelihatannya tidak dapat dibendung, sehingga panitia memutuskan untuk “mengamankan” sang “Lupus”. Saat itulah saya menyaksikan kejadian yang membuat saya merinding. Sambil digiring beberapa SATPAM, Hilman dilarikan ke sebuah ruangan lain, dan remaja-remaja yang kecewa karena tidak dapat melihat idola mereka, langsung menyerbu. Saya tidak berani melihatnya. Beberapa waktu kemudian, panitia memutuskan untuk mengeluarkan “Lupus” lagi. Dan akhirnya Hilman berdiri di atas panggung darurat di pinggir ruangan, dan di sekelilingnya berjaga petugas-petugas keamanan. Ditemani tokoh-tokoh “Lupus” lainnya, Hilman berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggemarnya. Saya lihat dia mengunyah permen karet, tapi saya tahu dia pasti merasa tegang. Sore itu dia sudah berubah menjadi “Lupus”, dan sejak itu pula saya menyadari bahwa dia sudah menjadi milik masyarakat.
Mulai saat itu, jalan-jalan dengan Hilman sudah tidak “aman” lagi. Pernah satu kali, ketika kami sedang beramai-ramai makan di restoran untuk merayakan ulang tahun salah seorang di antara kami, tiba-tiba pelayan restoran datang dengan selembar kertas yang langsung diberikannya kepada Hilman. Di atas kertas itu tertulis: “Kalau tidak salah, Kakak yang bernama Hilman, ya? Saya minta tanda tangannya, dong.” Serentak kami menoleh ke arah meja yang ditunjukkan pelayan, dan di sana seorang gadis tersenyum pada Hilman!
Sukses “Lupus” ternyata tidak hanya sampai di situ. Suatu malam Hilman datang ke rumah. Dandanannya sudah banyak berubah. Tampaknya dia mulai menerapkan apa yang digambarkannya di dalam “Lupus” pada dirinya sendiri. Kemejanya gombrong, rambutnya semakin gondrong, terutama di bagian depan. Saya tidak tahu apakah semua itu dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau tidak. Setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya Hilman mengatakan maksud kedatangannya. Sambil menyodorkan sebuah map, dia berkata, “Ta, kita mau ngajakin kamu ikutan main film.” (Hilman memang selalu menyebut dirinya dengan “kita”, bukan “saya”, “aku”, atau “gue”).
Saya setengah tidak percaya. Rupanya bukunya yang laris itu menarik minat seorang produser film untuk mengangkat cerita “Lupus” ke layar perak. Dan sutradara yang ditunjuk untuk itu beranggapan bahwa orang yang paling cocok memerankan tokoh “Lupus” adalah penciptanya sendiri, Hilman.
“Tapi kamu 'kan bukan ‘Lupus’, Man?” kata saya waktu itu, sebab saya tahu benar bahwa “Lupus” dan Hilman itu sangat berbeda. “Lupus” itu tipe cowok cuek, yang bisa iseng bersuit-suit menggoda cewek yang lewat. Sedangkan Hilman begitu pemalunya, sampai‑ sampai dia pernah mengurungkan niatnya menegur saya dan dua orang teman, hanya karena tidak mengenali salah seorang dari kami yang baru ganti model rambut! Dan mengenai kejadian ini, Hilman sempat menulis surat menyatakan penyesalannya.
Itulah Hilman. Saya baca map yang berisi skenario itu. Tapi dengan berat hati saya tolak ajakannya, karena jadwal kuliah saya terlalu padat, dan saya juga tidak merasa akan bisa ikut beraksi di depan kamera. Saya juga menyangsikan kemampuan Hilman untuk itu.
Kira-kira sebulan sesudah kejadian itu, bersama seorang teman saya datang ke rumahnya. Ketika kami berkomentar tentang rambutnya yang acak-acakan karena gondrong itu, Hilman menjawab dengan gayanya yang khas, polos, “Kemarin kita potong sedikit aja sutradaranya marah-marah.”
Hilman dan kawan-kawannya memang tidak jadi memerankan tokoh “Lupus” itu, namun dengan digantikannya kedudukan mereka dengan bintang-bintang film sungguhan, kabarnya film itu sukses juga. Sedangkan Hilman malah semakin menjadi public figure.
Suatu hari saya membaca di majalah remaja Hai bahwa Hilman akan memberikan ceramah dengan tema yang berkisar pada perkawinan di usia remaja. Ya, ampun! Apa lagi ini? Apa yang akan dibicarakannya? Apa yang dia tahu tentang perkawinan remaja? Dengan sedikit usaha, akhirnya saya berhasil menemukan asal-muasalnya mengapa Hilman sampai bersedia tampil sebagai salah seorang pembawa makalah. “Habis, disuruh sama Mbak Retno [salah seorang anggota redaksi Hai]. Dia sudah terlanjur nyanggupin panitianya.”
Terakhir saya bertemu dengan Hilman kira-kira setengah tahun yang lalu. Waktu itu dia datang ke rumah untuk meminjam tas. “Kita diajakin ikutan tur buat promosi film Lupus. Lumayan gratis,” katanya, “Kita, sih, maunya bawa tas kecil aja, tapi ibu kita nyuruh bawa tas koper,” sambungnya polos.
Saya tidak bisa tidak ketawa. Saya ambilkan dua buah travel bag saya, dan saya suruh dia memilih. Karena kelihatannya bingung, saya suruh dia membawa kedua tas itu. Untuk jangka waktu yang lama, itulah terakhir kalinya saya bertemu dengan Hilman, dan juga dengan kedua tas itu. Ketika akhirnya kedua tas itu kembali juga kepada saya, saya bahkan sudah lupa bahwa Hilman pernah meminjamnya dari saya.
Sumber: Marahimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
Oleh Rosita
Mahasiswa FSUI pengikut m.k. Penulisan Populer 1988/89
Bandung, lewat pukul sembilan malam. Kami berempat, Mirta, Marti, Hilman dan saya, sibuk mengaduk-aduk daerah pemukiman di sekitar Dago. Untuk ukuran Bandung, hari sudah terlalu larut, dan juga badan kami sudah capek setelah berjam-jam terguncangguncang di dalam bis yang membawa kami dari Jakarta. Tapi bayangan tempat tidur yang empuk tampaknya masih jauh, karena kami masih harus menemani makhluk cowok satu-satunya di dalam rombongan ini mencari rumah saudaranya untuk menginap. Ironis sekali. Seharusnya, dialah yang mengawal kami, cewek-cewek, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Hilman, yang tingkahnya kadang-kadang sering bikin orang geleng-geleng kepala.
Itu tiga setengah tahun yang lalu, ketika Hilman belum menulis mengenai tokoh yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan remaja: Lupus. Dan semenjak itu, perlahan-lahan Hilman menjadi semakin jauh.
Pertama sekali membaca cerita “Lupus” di majalah Hai, rasanya tidak ada yang terlalu istimewa di situ. Saya memang sudah lama menyukai tulisan Hilman, baik itu artikel, cerita pendek, atau pun cerita bersambung. Buat saya, gaya Hilman bercerita enak dibaca, sebab kata-kata yang dipakainya adalah yang saya jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Saya pikir, ketika itu, serial "Lupus" itu pun biasa-biasa saja. Saya tahu nama Hilman akan sering-sering muncul, tapi paling-paling hanya terbatas di majalah Hai saja. Belakangan terbukti bahwa perkiraan saya meleset total.
Cerita "Lupus" terus mengalir, dimuat setiap minggu di majalah Hai. Sementara itu pula, acara jalan-jalan dengan Hilman bersama teman-teman lain yang suka menamakan diri The Famous Five, masih berlangsung terus. Hilman memang tipe cowok 'pasrah' yang dengan rela menemani kami, empat cewek, jalan-jalan seharian di Ancol. Dia juga tidak banyak protes ketika saya ajak bergadang di Cibubur buat melihat komet Halley.
Tapi nasib menentukan lain buat Hilman. Cerita-cerita 'Lupus'-nya diterbitkan oleh Gramedia menjadi sebuah buku kecil dengan judul Tangkaplah Daku Kau Kujitak, dan laris bak kacang goreng. Dua minggu setelah dilempar ke pasaran, buku itu harus dicetak ulang, berkali-kali. Sejak itulah tokoh “Lupus” mulai sering Saya jumpai di mana-mana, tapi sejak itu pula Hilman mulai sulit ditemui.
“Lupus,” cowok SMA yang berbadan tinggi-ceking, berambut gondrong dan selalu mengunyah permen karet itu tiba-tiba saja diterima sebagai figur yang digandrungi di kalangan anak-anak SMP dan SMA.
Suatu hari Hilman datang ke rumah saya. Dia membawa beberapa kaos yang bergambar dan bertulisan “Lupus”, dan berpesan agar kaos-kaos itu dibagi-bagikan kepada anggota The Famous Five lainnya untuk dipakai pada acara “Jumpa Lupus”. “Tapi kamu mesti datang, lho. Kalo nggak kaosnya nggak dikasih,” katanya. Saya lihat-lihat, kaosnya lumayan bagus, karena itu saya sanggupi saja untuk datang ke acara itu.
Apa yang saya lihat pada acara “Jumpa Lupus” itu betul-betul di luar dugaan saya, dan sempat membuat saya merinding. Pukul empat sore. Lantai atas toko buku Gramedia di jalan Matraman sudah dipenuhi oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, pelajar SMP dan SMA. Di tengah ruangan, di atas meja yang disusun menjadi panggung, saya lihat Hilman berdiri dengan beberapa orang temannya, yang menampilkan perwujudan tokoh-tokoh di dalam cerita 'Lupus'-nya. Di sekeliling panggung, puluhan remaja mencoba menyerbu ke panggung.
Saya hampir tidak percaya bahwa sosok yang dielu-elukan gerombolan remaja itu adalah Hilman. Hilman yang malam tadi mengantarkan kaos ke rumah, Hilman yang pasrah dan telaten menemani kami, Hilman yang ....
Serbuan penggemar “Lupus” kelihatannya tidak dapat dibendung, sehingga panitia memutuskan untuk “mengamankan” sang “Lupus”. Saat itulah saya menyaksikan kejadian yang membuat saya merinding. Sambil digiring beberapa SATPAM, Hilman dilarikan ke sebuah ruangan lain, dan remaja-remaja yang kecewa karena tidak dapat melihat idola mereka, langsung menyerbu. Saya tidak berani melihatnya. Beberapa waktu kemudian, panitia memutuskan untuk mengeluarkan “Lupus” lagi. Dan akhirnya Hilman berdiri di atas panggung darurat di pinggir ruangan, dan di sekelilingnya berjaga petugas-petugas keamanan. Ditemani tokoh-tokoh “Lupus” lainnya, Hilman berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggemarnya. Saya lihat dia mengunyah permen karet, tapi saya tahu dia pasti merasa tegang. Sore itu dia sudah berubah menjadi “Lupus”, dan sejak itu pula saya menyadari bahwa dia sudah menjadi milik masyarakat.
Mulai saat itu, jalan-jalan dengan Hilman sudah tidak “aman” lagi. Pernah satu kali, ketika kami sedang beramai-ramai makan di restoran untuk merayakan ulang tahun salah seorang di antara kami, tiba-tiba pelayan restoran datang dengan selembar kertas yang langsung diberikannya kepada Hilman. Di atas kertas itu tertulis: “Kalau tidak salah, Kakak yang bernama Hilman, ya? Saya minta tanda tangannya, dong.” Serentak kami menoleh ke arah meja yang ditunjukkan pelayan, dan di sana seorang gadis tersenyum pada Hilman!
Sukses “Lupus” ternyata tidak hanya sampai di situ. Suatu malam Hilman datang ke rumah. Dandanannya sudah banyak berubah. Tampaknya dia mulai menerapkan apa yang digambarkannya di dalam “Lupus” pada dirinya sendiri. Kemejanya gombrong, rambutnya semakin gondrong, terutama di bagian depan. Saya tidak tahu apakah semua itu dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau tidak. Setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya Hilman mengatakan maksud kedatangannya. Sambil menyodorkan sebuah map, dia berkata, “Ta, kita mau ngajakin kamu ikutan main film.” (Hilman memang selalu menyebut dirinya dengan “kita”, bukan “saya”, “aku”, atau “gue”).
Saya setengah tidak percaya. Rupanya bukunya yang laris itu menarik minat seorang produser film untuk mengangkat cerita “Lupus” ke layar perak. Dan sutradara yang ditunjuk untuk itu beranggapan bahwa orang yang paling cocok memerankan tokoh “Lupus” adalah penciptanya sendiri, Hilman.
“Tapi kamu 'kan bukan ‘Lupus’, Man?” kata saya waktu itu, sebab saya tahu benar bahwa “Lupus” dan Hilman itu sangat berbeda. “Lupus” itu tipe cowok cuek, yang bisa iseng bersuit-suit menggoda cewek yang lewat. Sedangkan Hilman begitu pemalunya, sampai‑ sampai dia pernah mengurungkan niatnya menegur saya dan dua orang teman, hanya karena tidak mengenali salah seorang dari kami yang baru ganti model rambut! Dan mengenai kejadian ini, Hilman sempat menulis surat menyatakan penyesalannya.
Itulah Hilman. Saya baca map yang berisi skenario itu. Tapi dengan berat hati saya tolak ajakannya, karena jadwal kuliah saya terlalu padat, dan saya juga tidak merasa akan bisa ikut beraksi di depan kamera. Saya juga menyangsikan kemampuan Hilman untuk itu.
Kira-kira sebulan sesudah kejadian itu, bersama seorang teman saya datang ke rumahnya. Ketika kami berkomentar tentang rambutnya yang acak-acakan karena gondrong itu, Hilman menjawab dengan gayanya yang khas, polos, “Kemarin kita potong sedikit aja sutradaranya marah-marah.”
Hilman dan kawan-kawannya memang tidak jadi memerankan tokoh “Lupus” itu, namun dengan digantikannya kedudukan mereka dengan bintang-bintang film sungguhan, kabarnya film itu sukses juga. Sedangkan Hilman malah semakin menjadi public figure.
Suatu hari saya membaca di majalah remaja Hai bahwa Hilman akan memberikan ceramah dengan tema yang berkisar pada perkawinan di usia remaja. Ya, ampun! Apa lagi ini? Apa yang akan dibicarakannya? Apa yang dia tahu tentang perkawinan remaja? Dengan sedikit usaha, akhirnya saya berhasil menemukan asal-muasalnya mengapa Hilman sampai bersedia tampil sebagai salah seorang pembawa makalah. “Habis, disuruh sama Mbak Retno [salah seorang anggota redaksi Hai]. Dia sudah terlanjur nyanggupin panitianya.”
Terakhir saya bertemu dengan Hilman kira-kira setengah tahun yang lalu. Waktu itu dia datang ke rumah untuk meminjam tas. “Kita diajakin ikutan tur buat promosi film Lupus. Lumayan gratis,” katanya, “Kita, sih, maunya bawa tas kecil aja, tapi ibu kita nyuruh bawa tas koper,” sambungnya polos.
Saya tidak bisa tidak ketawa. Saya ambilkan dua buah travel bag saya, dan saya suruh dia memilih. Karena kelihatannya bingung, saya suruh dia membawa kedua tas itu. Untuk jangka waktu yang lama, itulah terakhir kalinya saya bertemu dengan Hilman, dan juga dengan kedua tas itu. Ketika akhirnya kedua tas itu kembali juga kepada saya, saya bahkan sudah lupa bahwa Hilman pernah meminjamnya dari saya.
Sumber: Marahimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
Hilman di Balik Lupus
In Profil PenulisSenin, 12 April 2010
 Oleh Rosita
Mahasiswa FSUI pengikut m.k. Penulisan Populer 1988/89
Bandung, lewat pukul sembilan malam. Kami berempat, Mirta, Marti, Hilman dan saya, sibuk mengaduk-aduk daerah pemukiman di sekitar Dago. Untuk ukuran Bandung, hari sudah terlalu larut, dan juga badan kami sudah capek setelah berjam-jam terguncangguncang di dalam bis yang membawa kami dari Jakarta. Tapi bayangan tempat tidur yang empuk tampaknya masih jauh, karena kami masih harus menemani makhluk cowok satu-satunya di dalam rombongan ini mencari rumah saudaranya untuk menginap. Ironis sekali. Seharusnya, dialah yang mengawal kami, cewek-cewek, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Hilman, yang tingkahnya kadang-kadang sering bikin orang geleng-geleng kepala.
Itu tiga setengah tahun yang lalu, ketika Hilman belum menulis mengenai tokoh yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan remaja: Lupus. Dan semenjak itu, perlahan-lahan Hilman menjadi semakin jauh.
Pertama sekali membaca cerita “Lupus” di majalah Hai, rasanya tidak ada yang terlalu istimewa di situ. Saya memang sudah lama menyukai tulisan Hilman, baik itu artikel, cerita pendek, atau pun cerita bersambung. Buat saya, gaya Hilman bercerita enak dibaca, sebab kata-kata yang dipakainya adalah yang saya jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Saya pikir, ketika itu, serial "Lupus" itu pun biasa-biasa saja. Saya tahu nama Hilman akan sering-sering muncul, tapi paling-paling hanya terbatas di majalah Hai saja. Belakangan terbukti bahwa perkiraan saya meleset total.
Cerita "Lupus" terus mengalir, dimuat setiap minggu di majalah Hai. Sementara itu pula, acara jalan-jalan dengan Hilman bersama teman-teman lain yang suka menamakan diri The Famous Five, masih berlangsung terus. Hilman memang tipe cowok 'pasrah' yang dengan rela menemani kami, empat cewek, jalan-jalan seharian di Ancol. Dia juga tidak banyak protes ketika saya ajak bergadang di Cibubur buat melihat komet Halley.
Tapi nasib menentukan lain buat Hilman. Cerita-cerita 'Lupus'-nya diterbitkan oleh Gramedia menjadi sebuah buku kecil dengan judul Tangkaplah Daku Kau Kujitak, dan laris bak kacang goreng. Dua minggu setelah dilempar ke pasaran, buku itu harus dicetak ulang, berkali-kali. Sejak itulah tokoh “Lupus” mulai sering Saya jumpai di mana-mana, tapi sejak itu pula Hilman mulai sulit ditemui.
“Lupus,” cowok SMA yang berbadan tinggi-ceking, berambut gondrong dan selalu mengunyah permen karet itu tiba-tiba saja diterima sebagai figur yang digandrungi di kalangan anak-anak SMP dan SMA.
Suatu hari Hilman datang ke rumah saya. Dia membawa beberapa kaos yang bergambar dan bertulisan “Lupus”, dan berpesan agar kaos-kaos itu dibagi-bagikan kepada anggota The Famous Five lainnya untuk dipakai pada acara “Jumpa Lupus”. “Tapi kamu mesti datang, lho. Kalo nggak kaosnya nggak dikasih,” katanya. Saya lihat-lihat, kaosnya lumayan bagus, karena itu saya sanggupi saja untuk datang ke acara itu.
Apa yang saya lihat pada acara “Jumpa Lupus” itu betul-betul di luar dugaan saya, dan sempat membuat saya merinding. Pukul empat sore. Lantai atas toko buku Gramedia di jalan Matraman sudah dipenuhi oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, pelajar SMP dan SMA. Di tengah ruangan, di atas meja yang disusun menjadi panggung, saya lihat Hilman berdiri dengan beberapa orang temannya, yang menampilkan perwujudan tokoh-tokoh di dalam cerita 'Lupus'-nya. Di sekeliling panggung, puluhan remaja mencoba menyerbu ke panggung.
Saya hampir tidak percaya bahwa sosok yang dielu-elukan gerombolan remaja itu adalah Hilman. Hilman yang malam tadi mengantarkan kaos ke rumah, Hilman yang pasrah dan telaten menemani kami, Hilman yang ....
Serbuan penggemar “Lupus” kelihatannya tidak dapat dibendung, sehingga panitia memutuskan untuk “mengamankan” sang “Lupus”. Saat itulah saya menyaksikan kejadian yang membuat saya merinding. Sambil digiring beberapa SATPAM, Hilman dilarikan ke sebuah ruangan lain, dan remaja-remaja yang kecewa karena tidak dapat melihat idola mereka, langsung menyerbu. Saya tidak berani melihatnya. Beberapa waktu kemudian, panitia memutuskan untuk mengeluarkan “Lupus” lagi. Dan akhirnya Hilman berdiri di atas panggung darurat di pinggir ruangan, dan di sekelilingnya berjaga petugas-petugas keamanan. Ditemani tokoh-tokoh “Lupus” lainnya, Hilman berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggemarnya. Saya lihat dia mengunyah permen karet, tapi saya tahu dia pasti merasa tegang. Sore itu dia sudah berubah menjadi “Lupus”, dan sejak itu pula saya menyadari bahwa dia sudah menjadi milik masyarakat.
Mulai saat itu, jalan-jalan dengan Hilman sudah tidak “aman” lagi. Pernah satu kali, ketika kami sedang beramai-ramai makan di restoran untuk merayakan ulang tahun salah seorang di antara kami, tiba-tiba pelayan restoran datang dengan selembar kertas yang langsung diberikannya kepada Hilman. Di atas kertas itu tertulis: “Kalau tidak salah, Kakak yang bernama Hilman, ya? Saya minta tanda tangannya, dong.” Serentak kami menoleh ke arah meja yang ditunjukkan pelayan, dan di sana seorang gadis tersenyum pada Hilman!
Sukses “Lupus” ternyata tidak hanya sampai di situ. Suatu malam Hilman datang ke rumah. Dandanannya sudah banyak berubah. Tampaknya dia mulai menerapkan apa yang digambarkannya di dalam “Lupus” pada dirinya sendiri. Kemejanya gombrong, rambutnya semakin gondrong, terutama di bagian depan. Saya tidak tahu apakah semua itu dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau tidak. Setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya Hilman mengatakan maksud kedatangannya. Sambil menyodorkan sebuah map, dia berkata, “Ta, kita mau ngajakin kamu ikutan main film.” (Hilman memang selalu menyebut dirinya dengan “kita”, bukan “saya”, “aku”, atau “gue”).
Saya setengah tidak percaya. Rupanya bukunya yang laris itu menarik minat seorang produser film untuk mengangkat cerita “Lupus” ke layar perak. Dan sutradara yang ditunjuk untuk itu beranggapan bahwa orang yang paling cocok memerankan tokoh “Lupus” adalah penciptanya sendiri, Hilman.
“Tapi kamu 'kan bukan ‘Lupus’, Man?” kata saya waktu itu, sebab saya tahu benar bahwa “Lupus” dan Hilman itu sangat berbeda. “Lupus” itu tipe cowok cuek, yang bisa iseng bersuit-suit menggoda cewek yang lewat. Sedangkan Hilman begitu pemalunya, sampai‑ sampai dia pernah mengurungkan niatnya menegur saya dan dua orang teman, hanya karena tidak mengenali salah seorang dari kami yang baru ganti model rambut! Dan mengenai kejadian ini, Hilman sempat menulis surat menyatakan penyesalannya.
Itulah Hilman. Saya baca map yang berisi skenario itu. Tapi dengan berat hati saya tolak ajakannya, karena jadwal kuliah saya terlalu padat, dan saya juga tidak merasa akan bisa ikut beraksi di depan kamera. Saya juga menyangsikan kemampuan Hilman untuk itu.
Kira-kira sebulan sesudah kejadian itu, bersama seorang teman saya datang ke rumahnya. Ketika kami berkomentar tentang rambutnya yang acak-acakan karena gondrong itu, Hilman menjawab dengan gayanya yang khas, polos, “Kemarin kita potong sedikit aja sutradaranya marah-marah.”
Hilman dan kawan-kawannya memang tidak jadi memerankan tokoh “Lupus” itu, namun dengan digantikannya kedudukan mereka dengan bintang-bintang film sungguhan, kabarnya film itu sukses juga. Sedangkan Hilman malah semakin menjadi public figure.
Suatu hari saya membaca di majalah remaja Hai bahwa Hilman akan memberikan ceramah dengan tema yang berkisar pada perkawinan di usia remaja. Ya, ampun! Apa lagi ini? Apa yang akan dibicarakannya? Apa yang dia tahu tentang perkawinan remaja? Dengan sedikit usaha, akhirnya saya berhasil menemukan asal-muasalnya mengapa Hilman sampai bersedia tampil sebagai salah seorang pembawa makalah. “Habis, disuruh sama Mbak Retno [salah seorang anggota redaksi Hai]. Dia sudah terlanjur nyanggupin panitianya.”
Terakhir saya bertemu dengan Hilman kira-kira setengah tahun yang lalu. Waktu itu dia datang ke rumah untuk meminjam tas. “Kita diajakin ikutan tur buat promosi film Lupus. Lumayan gratis,” katanya, “Kita, sih, maunya bawa tas kecil aja, tapi ibu kita nyuruh bawa tas koper,” sambungnya polos.
Saya tidak bisa tidak ketawa. Saya ambilkan dua buah travel bag saya, dan saya suruh dia memilih. Karena kelihatannya bingung, saya suruh dia membawa kedua tas itu. Untuk jangka waktu yang lama, itulah terakhir kalinya saya bertemu dengan Hilman, dan juga dengan kedua tas itu. Ketika akhirnya kedua tas itu kembali juga kepada saya, saya bahkan sudah lupa bahwa Hilman pernah meminjamnya dari saya.
Sumber: Marahimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
Oleh Rosita
Mahasiswa FSUI pengikut m.k. Penulisan Populer 1988/89
Bandung, lewat pukul sembilan malam. Kami berempat, Mirta, Marti, Hilman dan saya, sibuk mengaduk-aduk daerah pemukiman di sekitar Dago. Untuk ukuran Bandung, hari sudah terlalu larut, dan juga badan kami sudah capek setelah berjam-jam terguncangguncang di dalam bis yang membawa kami dari Jakarta. Tapi bayangan tempat tidur yang empuk tampaknya masih jauh, karena kami masih harus menemani makhluk cowok satu-satunya di dalam rombongan ini mencari rumah saudaranya untuk menginap. Ironis sekali. Seharusnya, dialah yang mengawal kami, cewek-cewek, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Hilman, yang tingkahnya kadang-kadang sering bikin orang geleng-geleng kepala.
Itu tiga setengah tahun yang lalu, ketika Hilman belum menulis mengenai tokoh yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan remaja: Lupus. Dan semenjak itu, perlahan-lahan Hilman menjadi semakin jauh.
Pertama sekali membaca cerita “Lupus” di majalah Hai, rasanya tidak ada yang terlalu istimewa di situ. Saya memang sudah lama menyukai tulisan Hilman, baik itu artikel, cerita pendek, atau pun cerita bersambung. Buat saya, gaya Hilman bercerita enak dibaca, sebab kata-kata yang dipakainya adalah yang saya jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Saya pikir, ketika itu, serial "Lupus" itu pun biasa-biasa saja. Saya tahu nama Hilman akan sering-sering muncul, tapi paling-paling hanya terbatas di majalah Hai saja. Belakangan terbukti bahwa perkiraan saya meleset total.
Cerita "Lupus" terus mengalir, dimuat setiap minggu di majalah Hai. Sementara itu pula, acara jalan-jalan dengan Hilman bersama teman-teman lain yang suka menamakan diri The Famous Five, masih berlangsung terus. Hilman memang tipe cowok 'pasrah' yang dengan rela menemani kami, empat cewek, jalan-jalan seharian di Ancol. Dia juga tidak banyak protes ketika saya ajak bergadang di Cibubur buat melihat komet Halley.
Tapi nasib menentukan lain buat Hilman. Cerita-cerita 'Lupus'-nya diterbitkan oleh Gramedia menjadi sebuah buku kecil dengan judul Tangkaplah Daku Kau Kujitak, dan laris bak kacang goreng. Dua minggu setelah dilempar ke pasaran, buku itu harus dicetak ulang, berkali-kali. Sejak itulah tokoh “Lupus” mulai sering Saya jumpai di mana-mana, tapi sejak itu pula Hilman mulai sulit ditemui.
“Lupus,” cowok SMA yang berbadan tinggi-ceking, berambut gondrong dan selalu mengunyah permen karet itu tiba-tiba saja diterima sebagai figur yang digandrungi di kalangan anak-anak SMP dan SMA.
Suatu hari Hilman datang ke rumah saya. Dia membawa beberapa kaos yang bergambar dan bertulisan “Lupus”, dan berpesan agar kaos-kaos itu dibagi-bagikan kepada anggota The Famous Five lainnya untuk dipakai pada acara “Jumpa Lupus”. “Tapi kamu mesti datang, lho. Kalo nggak kaosnya nggak dikasih,” katanya. Saya lihat-lihat, kaosnya lumayan bagus, karena itu saya sanggupi saja untuk datang ke acara itu.
Apa yang saya lihat pada acara “Jumpa Lupus” itu betul-betul di luar dugaan saya, dan sempat membuat saya merinding. Pukul empat sore. Lantai atas toko buku Gramedia di jalan Matraman sudah dipenuhi oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan, pelajar SMP dan SMA. Di tengah ruangan, di atas meja yang disusun menjadi panggung, saya lihat Hilman berdiri dengan beberapa orang temannya, yang menampilkan perwujudan tokoh-tokoh di dalam cerita 'Lupus'-nya. Di sekeliling panggung, puluhan remaja mencoba menyerbu ke panggung.
Saya hampir tidak percaya bahwa sosok yang dielu-elukan gerombolan remaja itu adalah Hilman. Hilman yang malam tadi mengantarkan kaos ke rumah, Hilman yang pasrah dan telaten menemani kami, Hilman yang ....
Serbuan penggemar “Lupus” kelihatannya tidak dapat dibendung, sehingga panitia memutuskan untuk “mengamankan” sang “Lupus”. Saat itulah saya menyaksikan kejadian yang membuat saya merinding. Sambil digiring beberapa SATPAM, Hilman dilarikan ke sebuah ruangan lain, dan remaja-remaja yang kecewa karena tidak dapat melihat idola mereka, langsung menyerbu. Saya tidak berani melihatnya. Beberapa waktu kemudian, panitia memutuskan untuk mengeluarkan “Lupus” lagi. Dan akhirnya Hilman berdiri di atas panggung darurat di pinggir ruangan, dan di sekelilingnya berjaga petugas-petugas keamanan. Ditemani tokoh-tokoh “Lupus” lainnya, Hilman berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggemarnya. Saya lihat dia mengunyah permen karet, tapi saya tahu dia pasti merasa tegang. Sore itu dia sudah berubah menjadi “Lupus”, dan sejak itu pula saya menyadari bahwa dia sudah menjadi milik masyarakat.
Mulai saat itu, jalan-jalan dengan Hilman sudah tidak “aman” lagi. Pernah satu kali, ketika kami sedang beramai-ramai makan di restoran untuk merayakan ulang tahun salah seorang di antara kami, tiba-tiba pelayan restoran datang dengan selembar kertas yang langsung diberikannya kepada Hilman. Di atas kertas itu tertulis: “Kalau tidak salah, Kakak yang bernama Hilman, ya? Saya minta tanda tangannya, dong.” Serentak kami menoleh ke arah meja yang ditunjukkan pelayan, dan di sana seorang gadis tersenyum pada Hilman!
Sukses “Lupus” ternyata tidak hanya sampai di situ. Suatu malam Hilman datang ke rumah. Dandanannya sudah banyak berubah. Tampaknya dia mulai menerapkan apa yang digambarkannya di dalam “Lupus” pada dirinya sendiri. Kemejanya gombrong, rambutnya semakin gondrong, terutama di bagian depan. Saya tidak tahu apakah semua itu dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau tidak. Setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya Hilman mengatakan maksud kedatangannya. Sambil menyodorkan sebuah map, dia berkata, “Ta, kita mau ngajakin kamu ikutan main film.” (Hilman memang selalu menyebut dirinya dengan “kita”, bukan “saya”, “aku”, atau “gue”).
Saya setengah tidak percaya. Rupanya bukunya yang laris itu menarik minat seorang produser film untuk mengangkat cerita “Lupus” ke layar perak. Dan sutradara yang ditunjuk untuk itu beranggapan bahwa orang yang paling cocok memerankan tokoh “Lupus” adalah penciptanya sendiri, Hilman.
“Tapi kamu 'kan bukan ‘Lupus’, Man?” kata saya waktu itu, sebab saya tahu benar bahwa “Lupus” dan Hilman itu sangat berbeda. “Lupus” itu tipe cowok cuek, yang bisa iseng bersuit-suit menggoda cewek yang lewat. Sedangkan Hilman begitu pemalunya, sampai‑ sampai dia pernah mengurungkan niatnya menegur saya dan dua orang teman, hanya karena tidak mengenali salah seorang dari kami yang baru ganti model rambut! Dan mengenai kejadian ini, Hilman sempat menulis surat menyatakan penyesalannya.
Itulah Hilman. Saya baca map yang berisi skenario itu. Tapi dengan berat hati saya tolak ajakannya, karena jadwal kuliah saya terlalu padat, dan saya juga tidak merasa akan bisa ikut beraksi di depan kamera. Saya juga menyangsikan kemampuan Hilman untuk itu.
Kira-kira sebulan sesudah kejadian itu, bersama seorang teman saya datang ke rumahnya. Ketika kami berkomentar tentang rambutnya yang acak-acakan karena gondrong itu, Hilman menjawab dengan gayanya yang khas, polos, “Kemarin kita potong sedikit aja sutradaranya marah-marah.”
Hilman dan kawan-kawannya memang tidak jadi memerankan tokoh “Lupus” itu, namun dengan digantikannya kedudukan mereka dengan bintang-bintang film sungguhan, kabarnya film itu sukses juga. Sedangkan Hilman malah semakin menjadi public figure.
Suatu hari saya membaca di majalah remaja Hai bahwa Hilman akan memberikan ceramah dengan tema yang berkisar pada perkawinan di usia remaja. Ya, ampun! Apa lagi ini? Apa yang akan dibicarakannya? Apa yang dia tahu tentang perkawinan remaja? Dengan sedikit usaha, akhirnya saya berhasil menemukan asal-muasalnya mengapa Hilman sampai bersedia tampil sebagai salah seorang pembawa makalah. “Habis, disuruh sama Mbak Retno [salah seorang anggota redaksi Hai]. Dia sudah terlanjur nyanggupin panitianya.”
Terakhir saya bertemu dengan Hilman kira-kira setengah tahun yang lalu. Waktu itu dia datang ke rumah untuk meminjam tas. “Kita diajakin ikutan tur buat promosi film Lupus. Lumayan gratis,” katanya, “Kita, sih, maunya bawa tas kecil aja, tapi ibu kita nyuruh bawa tas koper,” sambungnya polos.
Saya tidak bisa tidak ketawa. Saya ambilkan dua buah travel bag saya, dan saya suruh dia memilih. Karena kelihatannya bingung, saya suruh dia membawa kedua tas itu. Untuk jangka waktu yang lama, itulah terakhir kalinya saya bertemu dengan Hilman, dan juga dengan kedua tas itu. Ketika akhirnya kedua tas itu kembali juga kepada saya, saya bahkan sudah lupa bahwa Hilman pernah meminjamnya dari saya.
Sumber: Marahimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



















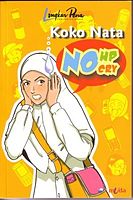
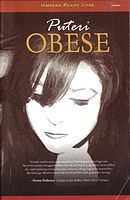
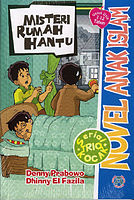


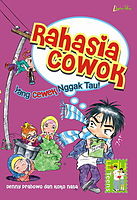


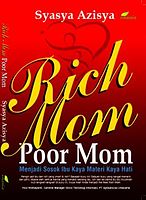



0 komentar:
Posting Komentar