Sumber: kolomkita.com
 Malam ini purnama sedang penuh. Bulan benderang begitu bundar. Bercahaya menyinari seperti lindungan ibu dalam dekapan yang menjelma dewi malam dan aku memperoleh restu di wajahnya yang bulat. Membuat langit hitam tak begitu gelap. Dalam rindang hutan pekat melarut lewat hembusan angin yang dingin. Bukan gulita sebab mataku masih bisa melihat. Hanya lindap dan kudapati kunang-kunang berkerlip, mengganti bintang yang tiada.
Malam ini purnama sedang penuh. Bulan benderang begitu bundar. Bercahaya menyinari seperti lindungan ibu dalam dekapan yang menjelma dewi malam dan aku memperoleh restu di wajahnya yang bulat. Membuat langit hitam tak begitu gelap. Dalam rindang hutan pekat melarut lewat hembusan angin yang dingin. Bukan gulita sebab mataku masih bisa melihat. Hanya lindap dan kudapati kunang-kunang berkerlip, mengganti bintang yang tiada.
Aku menantimu di batas Dusun Karampuang. Kau belum juga muncul padahal aku sudah lama menunggu di sini. Aku takut dan cemas. Itu sebabnya mataku terpaku pada ujung aspal yang menghilang seperti ingin menerobos malam yang teduh, mencari bayanganmu yang berkelebat, dan sesekali aku menengok ke belakang membaca situasi.
Rustam, tahukah kau? Di dalam sana, sunyi bukan berarti tidak ada bunyi walau tadi mereka sembunyi karena aku tak peduli. Bunyi hewan malam, nyanyian serangga, suara berdesis-desis yang bukan ular, kicau kao-kao yang mengerikan di rimbun daun di dalam hutan yang senyap, berbondong-bondong mengerubungi telingaku. Berdenting serupa dawai, mengalun dan merambati udara, dan bakal meninggalkan luka di hatiku bila kau tidak jadi menjemputku malam ini. Maka hadirlah di ujung jalan itu seperti dilahirkan oleh kabut yang merayap. Jangan sampai aku menjadi batu di sini karena gigil atau habis karena dimakan angin dan kau harus tahu jiwaku mulai beku meski sebenarnya kepalaku ingin meledak karena bosan. Aku tidak mungkin kembali setelah ingkar.
”Sepertinya lelaki itu tidak akan datang.”
Seseorang memegang bahuku dari belakang. Aku tersentak kaget dan terlonjak bangkit dari tugu batu yang kududuki. Aku gemetar gugup mengetahui siapa yang menegur.
”La Gole! Sedang apa kau di sini? Kau mengikutiku?” Sontak aku menjauhinya.
”Jubaedah, pulanglah sebelum terlambat. Masih ada kesempatan dan aku akan membantumu,” ujarnya sembari duduk di tugu batu yang kutinggalkan.
Dalam gelap aku tahu ia menatapku tajam, seruncing jarum yang pernah menusuk tanganku. Batinku tertohok mengingat ia adalah mata-mata Puang Gella, pemangku yang sering menghukum bila ada orang yang melanggar di kawasan dusun, meski ia temanku sejak kecil dan beberapa waktu silam aku menyimpan hati untuknya. Namun ia menunjukkan sikap yang tidak kusuka. Ia bukan lelaki tangguh, pengecut yang tidak berani mengajakku kawin lari.
”Benar kau akan menolongku?” tanyaku pura-pura ragu.
”Kau tidak percaya padaku?” La Gole menghampiriku begitu dekat hingga bisa kuhirup bau badannya yang belum disentuh sungai. Aroma napasnya purba.
”Baiklah kalau begitu. Ijinkan aku menunggu Rustam sebentar lagi,” pintaku. Lalu kedua kakiku tak mau diam karena gelisah.
”Jika dia tidak muncul?”
”Kau boleh membawaku pulang!” jawabku sedikit kesal.
”Sepakat.”
Agak lama kami saling diam seolah jiwa kami raib meninggalkan raga yang kikuk, menguak hutan dengan lesat untuk menemukanmu dengan tujuan yang berbeda. Kuperhatikan La Gole sedang duduk bersila sambil mempermainkan parang bersarung yang biasanya terlilit di pinggangnya. Tidak kutahu apa maksudnya, tapi membuatku bergidik membayangkan kulitmu robek dan menumpahkan darah jika badik itu keluar dari sarangnya. Kau pasti akan kalah sebab La Gole bekerja dengan otot sedangkan kau lebih suka berpikir.
”Apa yang kalian lakukan jika sudah bertemu? Apakah kau akan lari dengannya?” La Gole mengajukan tanya yang menyelidik, memecah hening. Posisi duduknya sudah berubah, satu kakinya berdiri dengan lutut menekuk.
”Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mau mengatakan sesuatu?” balasku berbohong sebab ia sudah curiga.
”Apa itu?”
”Kau tidak perlu tahu. Kenapa kau bertanya-tanya?”
”Ingin tahu saja. Bagaimanakah perasaanmu padanya?”
”Itu bukan urusanmu!” teriakku nyaris menuding, membuatnya bungkam.
Aku berbalik arah membelakanginya menahan amarah, antara jengkel dan putus asa. Kusandarkan kepalaku pada pohon yang tak bisa kurangkul. Aku mencabut-cabuti kulit keringnya yang berlumut dan memang sudah terkelupas, membuang geram. Mataku terasa panas bagai diperciki biji lombok. Pedih memerih.
Sekarang aku tidak ingin kau datang sebab itu akan mengantarkan nyawamu. Namun aku juga butuh kau datang membawaku pergi dari sini, jangan biarkan aku berkalung rantai. Aku tidak mau menjadi perawan tua! Bagaimana ini? Aku galau.
Tetapi tunggu. Mataku yang melirik menangkap bayangan sekilas, bersijingkat dan menunduk mirip gerak-gerik babi hutan, berpindah dengan cepat ke semak-semak. Apakah itu kau? Tidak sebentar aku terpana, dadaku berdesir dengan degupnya. Aku merasakan firasat tak baik. Aku mesti bersiasat.
”Aku menyerah. Seperti katamu, Rustam tidak datang. Mari pulang.” Sebisa mungkin kukulum senyum ini dan menampakkan muka murung agar tidak ketahuan, supaya kau dapat mengikutiku dari jarak jauh. Aku akan mengecohkan perhatiannya.
”Aku masih setia menemanimu menunggu jika kau mau?” Aku tahu ia mengejekku.
”Tidak usah! Barangkali dia pecundang yang lebih darimu.”
”Bagus kalau kau sadar. Orang kota memang tidak bisa dipegang janjinya!” timpalnya tak mau kalah.
Aku tidak lagi menyahut dan berjalan lebih dulu. Rustam, susul aku di puncak bukit!
***
Jubaedah, kau adalah gadis sunyi. Semerbak harum bunga desa, wangi menebarkan angan di setiap kepala jantan muda sepertiku. Aku menemukanmu bagai mutiara diantara ribuan kerikil bebatuan yang terserak di tepi kali. Namun ada yang hilang di wajahmu yang bulat langsat. Laksana embun pagi yang tak ada lagi, saat matahari tak bisa lagi disebut mentari. Aku seperti pangeran yang menemukan bidadari.
Di batas Dusun Karampuang jalanan beraspal terputus seperti lorong buntu. Terdapat daun kelapa yang diikat merintang di atas jalan. Mobil dinas kuparkir di luar kawasan adat karena dilarang masuk. Lagi pula hanya ada jalan setapak yang sempit. Tanahnya berdebu di musim kemarau dan licin berlumpur di musim penghujan. Banyak bebatuan. Di hari-hari biasa dusun ini begitu sepi bak kampung yang bisu.
Awal bulan November aku kembali. Aku sudah menjadi pegawai negeri di kabupaten. Setahun yang lalu aku datang di kampung ini untuk menyusun skripsiku mengenai adat Karampuang. Setelah lulus kuliah tak mampu kutahan hasrat hatiku, ingin kembali menggapaimu. Masihkah kau menjadi perawan suci yang tidak boleh dijamah?
Kutinggalkan semua yang berbau teknologi dan barang yang terkesan mewah di mobil sebelum memasuki kawasan adat yang dikeramatkan ini, lantaran pamali. Menurut keyakinan orang sini, segala yang datang dari luar lebih banyak merusak dan akan mengubah tatanan tradisi yang mereka jaga selama berabad-abad, turun temurun. Itu sebabnya aliran listrik tidak bisa masuk karena kaum adat menolak. Sungguh dilema, mengingat aku memegang proyek dari Pemda untuk menjadikan Karampuang tempat wisata, yang mungkin bakal melunturkan kebiasaan dan kepercayaan penduduk di dusun ini meski dengan maksud memberdayakan masyarakat.
Aku masih terkenang ketika pertama kali datang di kampung ini. Aku disambut dengan ramah. Tidak kurang isi baki sudah ditambah, belum setengah isi gelas sudah diimbuh. Aku yang mengetuk pintu bukanlah orang lain, malah dianggap keluarga sendiri. Sebab mereka memandang tamu itu membawa rezeki. Saat itu aku menumpang tidur di rumah ayahmu di luar kawasan adat, di dusun tetangga. Lantaran aku butuh listrik buat menyalakan laptopku, menulis hasil riset yang kudapat. Pernah aku menginap di rumah seorang warga. Alat penerangnya berupa lampu minyak yang mereka sebut sulo. Semalam suntuk aku menulis di lembar kertas. Pulang pagi-pagi. Kau berada di depan pintu. Tergelak tawamu melihatku. Suaramu renyah.
”Ada yang lucu?”
Kau tidak menjawab tapi memberikan isyarat. Kau pegang hidungmu yang mungil dan bangir. Aku mengikuti. Astaga, cuping hidungku dipenuhi asap hitam. Aku lekas pergi ke belakang membasuh muka.
Seminggu dalam sebulan, kita bertemu. Kau melepas masa haidmu di rumah. Parasmu demikian sendu seperti tidak terima seperti terpaksa, saat kau mengatakan sedang menuntut ilmu untuk kelak menjadi seorang sanro di rumah adat Karampuang. Rumah panggung yang merupakan simbol sosok perempuan. Dari jauh kediaman yang sakral itu memang tampak anggun. Atapnya dari anyaman daun nyiur berbentuk segitiga sama kaki. Tangganya terletak di tengah di kolong rumah.
”Tangga naik ke dalam rumah adalah kelamin perempuan,” jelas La Gole, temanmu.
Ia pemandu yang baik, meladeni keingintahuanku dan bahkan memuntahkan semua yang ia tahu. Pemuda yang bersemangat meski entah kenapa diam-diam ia sering menatapku dengan pandangan menghunus seperti tidak suka seperti menaruh curiga. Ia membicarakan tubuh perempuan dengan sangat biasa.
Membuka pintunya pun harus ditolak ke atas biar bergeser. Aku menebak pasti ini selaput dara kemaluan, sebab dibutuhkan sedikit usaha untuk membukanya. Ada batu bundar yang menindih.
”Arah dapur adalah rahim. Dan dua dapur di belakang itu adalah buah dada sebagai sumber kehidupan.”
Rumah ini tak bersekat, hanya ruang. Lantai dan dinding terbuat dari bambu. Ada loteng yang lumayan luas seperti layak untuk dijadikan kamar, tempat persimpanan kebutuhan pokok terutama padi. Bahkan ada padi yang berumur seabad.
”Semua warga sehabis panen tanpa diminta menyimpan sebagian padinya di sini untuk digunakan bersama jika terjadi gagal panen. Padi ini tidak boleh di jual.”
Aku ingin sekali mengabadikan apa yang aku lihat. Namun lelaki yang terbiasa bertelanjang dada saat bekerja di sawah ini melarangku dengan tegas. Badannya yang berotot dengan kulit secoklat kayu itu langsung tegap menantang.
”Jangan coba-coba bawa kamera. Itu kesepakatan kita dari awal. Boleh jadi kau yang melanggar, kami sekampung yang kena malapetaka. Kalau kau mau lama di sini hormati adat kami!”
Belum sempat aku minta maaf, La Gole sudah berlalu. Kulihat punggungnya digerogoti jamur, bercak-bercak putih.
Ketika kuceritakan penjelasan La Gole kepadamu, kau tersenyum simpul membenarkan. Pipimu merona seperti lembayung yang memerah bagai senja yang membakar langit. Aku jatuh hati.
Upacara Mappugau Sihanua sepertinya sudah dimulai. Selama tujuh hari tujuh malam. Aku berjalan santai menikmati pagi yang mau pergi. Sepanjang jalan yang berkelok kulewati rumah penduduk yang kadang saling berjauhan. Tak jarang aku berpapasan dengan warga yang masih kukenal. Di kiri kanan diselingi tanaman sayuran, pohon pisang, pohon kopi dan pohon kakao, serta hamparan sawah yang tidak rata, berundak-undak dengan garis pematang meliuk, sejauh mata memandang. Ada sumur tua berdinding susunan batu, aku menyebutnya kolam karena dangkal. Bila airnya lagi penuh, penduduk memandikan anaknya dan bayi yang baru lahir, biar mendapat berkah. Air mengalir khas pegunungan terdengar jernih menggelitik kesegaran. Hutan lebat dan belukar liar tampak rimbun di puncak bukit, hijau nian seperti belum pernah disinggahi. Jubaedah, secantik apa kau sekarang?
***
Lelaki itu masih gagah. Badannya berisi dan kulitnya bersih seperti pasir laut, seperti belum pernah dicubit matahari. Kini aku yakin kau makin terpikat, melirik pakaiannya yang sewarna kulit sapi. Lelaki idaman yang menggiurkan bunga desa sepertimu. Dan aku terhempas ibarat hati yang terbuang. Sebab cintaku sedang cemburu.
Ah, lelaki bernama Rustam itu terlalu mau tahu tentang adat kita dan ia sebarkan ke mana-mana. Aku tidak menyukainya karena itu, dan sebab ia mencuri hatimu dariku. Lebih dari itu, ia juga mencuci otakmu hingga pikiranmu telah kota walau disebabkan juga karena kau pernah sekolah sampai SMA di kabupaten. Kau pernah menjadi guru di dusun sebelah, mengajari kami baca tulis di usia kami yang sudah berkumis.
Kabarnya, Rustam akan mendirikan pasar rakyat dan penginapan di sekitar kampung ini. Makin ramai saja orang datang ke sini. Melihat kami sebagai tontonan. Melihat upacara kami sebagai pesta. Oh, Karampuang bagaimana nasibmu nanti? Ketika kebiasaan orang kota meracuni adat kami, menjarah apa yang kami jaga, yang kami miliki. Aku ingin sekali mengumpat, mereka tidak beradab karena mereka biadab!
Mungkin kelak tidak ada lagi yang namanya gotong royong. Seperti yang pernah dihimbau orang dulu, ”Hai sekalian anakku, kasih mengasihilah, rebah saling membangkitkan, hanyut saling mendamparkan, berkata saling mengiyakan, dan berbuat saling bantulah. Khilaf saling mengingatkan, satu kata dengan perbuatan, bagaimana di dalam begitu pula di luar, tegakkanlah yang keramat, sandarkanlah yang tabu, dan dudukkanlah yang makruh.”
Sekarang banyak yang mengerjakan sawah dengan cara bagi hasil, tidak lagi yang punya hajat memberi makan untuk disantap bersama. Begitu pula saat membangun rumah, menggunakan tenaga upah. Mengumpulkan puing-puing harta sehingga saling mencekik. Serakah sehingga saling menutup pintu.
Oh, Tomatoa! Hanya kamu yang murni. Kami akan teguh, tidak akan memasang paku tetap memakai tali rotan untuk menyusun kerangkamu. Mengganti tiangmu yang lapuk dengan menebang pohon bertuah di rimba melalui upacara madduik, menarik kayu bersama di hutan, wujud satu rasa. Tidak dipikul, sebab dipundak tanda mau menang sendiri. Oh, Tomatoa, kamu perempuan luhur yang kami puja. Dan kau, Jubaedah adalah perempuan Kampung Karampuang yang dijunjung. Darahmu adalah darah To Manurung. Mulia atas nama adat. Dan adat mengajarkanku tentang hidup, tidak mungkin kukhianati. Aku mencintaimu sebagaimana aku memegang adat. Disela itu terselip keinginan, yakni memilikimu yang tak boleh. Mencintai dan menginginkan itu serupa tapi tidak sama. Mengertikah, kau?
***
Aku bukanlah Maryam dan kenapa pula sejarah harus berulang? Tuhan, bolehkah aku mengeluh sebab sudah lama aku berpeluh? Aku tidak bangga dilahirkan sebagai makkunrai, perempuan. Tubuhku menyiksaku. Aku dibelenggu.
Ayah dan Ibu yang berbuat, mengapa aku yang harus jadi tumbal? Apakah memang dibutuhkan orang lain untuk menebus dosa? Lantas, salahkah mereka? Kau bisikkan di telinga Arung, tetua adat kami yang jarang bicara itu, untuk menentukan garis hidupku yang mesti kujalani. Menjadi perempuan suci, perempuan yang terkunci supaya tetap perawan. Jangan sampai sesuatu yang asing menyelinap masuk sebab akan melunturkan tradisi. Titah yang tak terbantahkan kecuali kalau aku cacat moral. Karena nanti warga juga yang akan memilih. Dan Ayah, Ibu, tak pernah membelaku. Ia wafat dengan patuh meski ia tak patut dipanggil Ayah, sebab tak pernah risau atau tak mau tahu jeritan hati anak gadisnya. Ayah memilih diam sampai ia menutup usia. Ayah hanya melihatku tumbuh.
Dan aku memilih, berontak seperti ibu. Ibu yang mati karena melahirkanku. Ibu yang kawin dengan kaum pendatang dan dikucilkan di desa tetangga. Ibu yang dipaksa bernazar, jika bayinya perempuan akan diambil sebagai penggantinya. Dan Kau, Tuhan, mengabulkannya…
Tetapi tidak! Sebagai anak aku merasa berkewajiban melanjutkan perjuangannya. Memang Puang Sanro telah renta, sudah layak istirahat. Perlu diganti. Tetapi mengapa harus aku? Tidak bolehkah orang lain? Aku selalu ingin bertanya kepada Puang Sanro tapi aku urung dalam hati, apakah ia memendam apa yang aku pendam? Ah, tentu tidak. Sebab aku tahu dari orang-orang, Puang Sanro adalah perempuan yang tidak laku.
”Dalam darahmu mengalir darah To Manurung, Anakku. Ikutilah takdirmu sebagaimana air yang mengalir,” ucapnya bernasihat ketika aku sedang malas meramu obat.
”Betapa menyenangkannya membantu orang, Anakku. Itu akan membuatmu menjadi ada,” lanjutnya berpesan di hari yang lain saat aku enggan mempelajari mantra-mantra.
Ketika menolong, haruskah berkorban? Cukup! Aku tak mau mendengar lagi. Aku mau tuli saja, sambil dalam benak ini bertekad, aku akan melawan arus. Aku mesti berupaya meski tangis mendahului.
Ya, sebab aku hanyalah perempuan biasa meski aku adalah perempuan yang cantik. Kusadari itu karena banyak yang merayuku semasa SMA dulu. Tapi aku tak hanyut. Aku mesti hati-hati meniti sebelum salah melangkah. Maka kutambatkan cintaku pada sahabat kecilku, La Gole. Aku sering memperhatikannya sampai-sampai aku tak sadar tubuhnya telah perkasa. Jika kami sedang berjalan beriringan aku senantiasa mendongak untuk melihatnya berbicara. Telingaku akan mendengar suara beratnya yang menentramkan. Andaikan aku dipeluk, pasti aku akan tenggelam dalam bahunya yang lebar. Saat kulit cokelat legamnya berkeringat, aku mencium bau khas manusia. Pernah juga ia menggenggam tanganku erat, sesaat tapi kurasakan kehangatan yang kokoh hingga jiwaku melambung. Hanya lidahku yang belum menafsirkan apa-apa. Namun ia tidak punya nyali, sikapnya terlalu lugu tak sebanding dengan badannya yang garang.
”La Gole, kau ada hati denganku?”
“Ya. Aku sayang kamu.”
“Kalau begitu bawa aku pergi dari sini.”
“Aku tidak punya kampung selain dusun ini.”
“Tinggal di hutan pun tak apa, asal bersamamu.”
“Tidak bisa. Tanah ini adalah orangtuaku.”
“Ah, kau tidak mencintaiku sebab cinta itu perlu bukti.”
”Aku tidak perlu membuktikannya karena cinta soal hati, dan itu cukup buatku.”
”Bagiku tidak. Kau bohong! Aku membencimu.”
Aku gigit jari. Aku kecewa dan patah hati.
Lalu muncul dia. Lelaki dari kota. Hadir dengan senyumnya yang menawan memberi harapan. Kulitnya harum dan langsat sepertiku. Kerap kubayangkan bila kami menyatu tak ada yang tahu bahwa kami berdua, bukan satu tubuh. Dan tentu saja ia hangat, antara panas dan lembap. Ia lapar dan aku haus, di hubungan kami yang sempat terjeda. Cukup lama hingga rindu mendera.
Kini malam sungguh malam karena awan yang menenteng air berlayar di langit kelam. Mengaburkan cahaya ibu di atas sana hingga buram. Lepas maghrib, pelita rumah penduduk memang sudah padam. Obor La Gole yang menuntun jalan juga telah redup. Kami tiba di sekitar rumah adat Karampuang.
”Kau tunggu di sini sebentar.” La Gole pergi menengok, mencari cara agar aku tidak terlacak sudah kabur.
“Jangan Lama,” kataku setelah ia agak menjauh, pura-pura khawatir.
Ah, lelaki itu memang baik tapi aku harus pamit mengejarmu. Berangkat diam-diam. Aku berlari dengan kain terangkat mengangkangi tanah yang kupijak, kendati sesekali terjungkal karena kesandung akar pohon yang mencuat. Hujan mengejarku seperti mengutuk.
Rustam, kau sudah berada di puncak bukit itu. Banyak peti batu berundak-undak di tempat ini, makam nenek moyang kami yang luhur. Kau basah kuyup sama denganku oleh derai hujan. Ada senter di tanganmu. Ternyata di atas sini tidak terlalu gelap seperti temaram. Paling tidak aku dapat melihat bayanganmu. Sementara jarum-jarum langit masih menyerbu, mengguyur deras, jatuh merintik terdengar menitik dan menerabas. Angin bertiup meliuk sangat kencang. Kau segera memelukku.
“Maafkan aku, datang tidak tepat waktu. La Gole mencegat dan mengancamku sebelum masuk desa. Karena aku, kita terjebak di sini.”
“Tak apa. Bukan salahmu.”
“Sekarang aku siap membawamu pergi.”
“Tidak. Jangan sekarang, di bawah sana begitu rawan. Di sini kita aman.”
”Lalu kau mau kita menunggu di sini sampai pagi?”
”Mungkin. Rustam, aku meminta sesuatu.”
”Apa itu? Akan kupenuhi.”
”Wisuda aku menjadi perempuan seutuhnya, malam ini juga.”
Apakah rasa sakit itu? Bila hasrat terjerembap, ketika birahi yang terpendam peka pada setiap ransangan. Melelehkan kebekuan dan meruntuhkan kekakuan. Aku gigil oleh getar. Di gubuk tua itu, tempat biasanya sesajian di letakkan, aku rebah menerimamu. Sesajen yang baru tadi siang, berhamburan karena ulah kita. Aku ingin perbuatan ini sakral seperti kematian. Rinai-rinai bersenandung seperti berkisah. Aku adalah hikayat perempuan tanpa biduk yang terdampar setelah lelah mengarungi duka. Kini aku luka dan hina. Tak perlu airmata sebab akan kutanggung semuanya.
”Terima kasih,” ucapku setelah usai.
Dan sudah kuduga. Semua makhluk punya mata. Senang mengintip yang terlarang. Lantaran nista mengusik siapa pun sebab baunya tercium tajam. Di kejauhan terlihat obor berkeliaran serupa kunang-kunang. La Gole muncul menaruh mata badik di lehermu. Mukanya murka. Aku mendorongmu supaya terhindar dan langsung melindungimu. Kita berjalan mundur menuju tebing.
***
Puang Sanro pernah meramalkan. Jika perempuan tidak kembali ke dapur, lebih senang keluyuran atau suka berkumpul, maka rentan berbuat dosa. Dan kau, Jubaedah sudah melakukan lebih dari itu. Kau telah haram di hatiku yang meradang. Ah, sebetulnya aku ingin menabur benih di pucukmu yang kuncup. Di tanahmu yang subur bakal tumbuh tanaman berbuah, darah dagingku. Kau memandikan bayi kita di sumur tua yang berkah itu supaya kelak menjadi anak yang patuh. Aku membajak sawah, menanam dan menuai padi, anak kita yang mengembala ternak, dan kau datang membawa makanan. Seandainya saja kau tahu angan-anganku yang sederhana ini, yang tak mungkin terwujud. Dan segalanya sirna saat kudapati pakaianmu berceceran ke mana-mana.
”Bangsat kau, Rustam. Kubunuh kau!”
”Berani menyentuhnya, aku lompat dalam jurang.”
Kau mengancam dan aku masih hirau. Aku merintih dalam amuk saat kau menyuruh Rustam hengkang dari kampung ini tanpa dijera. Kulempar lelaki durjana itu dengan sekepal batu hingga ia tersungkur, lalu bangkit tersaruk-saruk. Kau telah mendurhakai tanah keramat ini, sadarkah kau? Argh! Jubaedah, wajahmu yang bersinar dalam balutan pakaian putih yang menyejukkan hari-hariku kala memandangmu telah berubah busuk bagai bangkai. Kelak, kau dianggap tidak pernah ada.
Hari berganti, begitu pun bulan berlalu, dan tahun terus bertambah. Sejak peristiwa malam itu, namamu tak pernah lagi disebut nyaris dilupakan. Kau dikurung di rumah adat Karampuang di atas loteng untuk dikuduskan kembali entah sampai kapan. Tidak seorang pun diperkenankan menemuimu dan tak ada yang tahu bagaimana rupamu sekarang. Hingga pada suatu pagi, kami dikejutkan oleh kehadiran seorang bocah yang belum pernah kami lihat sebelumnya, muncul begitu saja, turun dari tangga rumah adat Karampuang bagai baru dilahirkan. Melihat dunia luar dengan muka gembira. Berlari lincah, berkeliaran seperti ingin mencari ayahnya.
***
Depok, 270908
(Kutulis ketika merindukan kampung halaman)
Catatan:
Karampuang: dusun yang terletak di puncak bukit 1000 meter dari permukaan laut, di Desa Tompobulu kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Masih memegang adat kuno dan alergi dengan teknologi. Rumah adatnya menyimbolkan sosok perempuan yang harus dijaga kehormatannya.
Mappugau Sihanua: Setiap tahun di pekan pertama bulan November diadakan pesta sebelum bercocok tanam setelah menikmati panen melimpah sebagai tanda syukur, tujuh hari tujuh malam.
Puang: kata sandang untuk orang yang dituakan atau yang dihormati.
Gella: pemangku yang melaksanakan hukum yang berlaku di Karampuang.
Arung: ketua adat atau raja yang jarang bicara tapi sekali bicara adalah tuah yang tak terbantahkan. Hidup matinya Karampuang ada di tangannya.
Sanro: pemimpin spritual di setiap prosesi adat yang harus dijabat oleh perempuan atau lebih tepatya disebut dukun.
To Manurung: nenek moyang orang Karampuang berwujud perempuan.
Tomatoa: nama rumah adat Karampuang.



















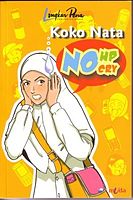
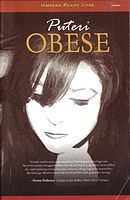
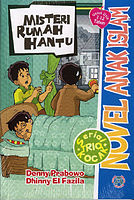


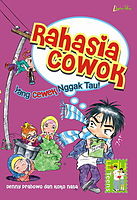


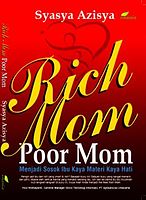



0 komentar:
Posting Komentar