Kristal-kristal bening menetes, menderas, menganak sungai di kedua belah pipiku. Setangkup sesal menyelinap ke dalam kalbu. Aku sudah menyakiti hati wanita yang sekian lama memeram luka di hatinya. Tangisku pun meledak.
 Senja menyemburat di antara mega yang arak-berarak. Cakrawala bagai lautan cahaya berwarna keemasan. Lempengan bola api raksasa itu melesap sebagian ditelan atap-atap bangunan rumah bertingkat yang tumbuh subur di pingiran sebuah kampus universitas negeri ternama di kota Depok.
Aku berada di sebuah kamar kos di lantai 2 sebuah rumah, memandangi senja dengan hati rengsa. Habis sudah kesabaranku menghadapi sikap kaku Mama. Kutinggalkan rumah. Kutinggalkan Mama. Keputusan yang sulit memang. Tanpa kusadar, air mata meretas dari kelopak mataku.
“Sampai kapan kamu mau terus melamun di depan jendela itu?” Suara lembut seorang wanita menggugah lamunanku. Mbak Kinan menutup pintu kamar.
Aku menyapu air mata yang melinang dengan jemariku. Mbak Kinan menghampiriku. Jemarinya lembut mengusap poni yang jatuh di keningku.
“Sudah. Jangan bersedih,” katanya berusaha menghiburku. “Nih, Mbak bawakan martabak telor. Kamu suka kan martabak telor?”
Aku mengangguk. Ia memberikan kantong plastik berisi martabak telor kepadaku.
“Jadi merepotkan.”
“Mbak senang kok direpotin sama kamu,” katanya tersenyum.
Ah, Mbak Kinan… seandainya saja Mama selembut dirimu…
Mbak Kinan mahasiswi sastra Inggris di sebuah universitas negeri di kota ini. Kedua orangtuanya membuka rumah makan khas Yogya di Tanah Suci. Seorang adik laki-lakinya tinggal di Yogya dengan neneknya. Mahasiswa semester akhir itu tinggal seorang diri di kamar kosnya, walaupun sebenarnya dia bisa saja manumpang di rumah pakde atau budenya. “Biar bisa mandiri,” begitu katanya. Selain sibuk sebagai asisten dosen, wanita berjilbab itu memberikan les privat Bahasa Inggris kepada anak-anak di sekitar tempat kosnya.
Senja menyemburat di antara mega yang arak-berarak. Cakrawala bagai lautan cahaya berwarna keemasan. Lempengan bola api raksasa itu melesap sebagian ditelan atap-atap bangunan rumah bertingkat yang tumbuh subur di pingiran sebuah kampus universitas negeri ternama di kota Depok.
Aku berada di sebuah kamar kos di lantai 2 sebuah rumah, memandangi senja dengan hati rengsa. Habis sudah kesabaranku menghadapi sikap kaku Mama. Kutinggalkan rumah. Kutinggalkan Mama. Keputusan yang sulit memang. Tanpa kusadar, air mata meretas dari kelopak mataku.
“Sampai kapan kamu mau terus melamun di depan jendela itu?” Suara lembut seorang wanita menggugah lamunanku. Mbak Kinan menutup pintu kamar.
Aku menyapu air mata yang melinang dengan jemariku. Mbak Kinan menghampiriku. Jemarinya lembut mengusap poni yang jatuh di keningku.
“Sudah. Jangan bersedih,” katanya berusaha menghiburku. “Nih, Mbak bawakan martabak telor. Kamu suka kan martabak telor?”
Aku mengangguk. Ia memberikan kantong plastik berisi martabak telor kepadaku.
“Jadi merepotkan.”
“Mbak senang kok direpotin sama kamu,” katanya tersenyum.
Ah, Mbak Kinan… seandainya saja Mama selembut dirimu…
Mbak Kinan mahasiswi sastra Inggris di sebuah universitas negeri di kota ini. Kedua orangtuanya membuka rumah makan khas Yogya di Tanah Suci. Seorang adik laki-lakinya tinggal di Yogya dengan neneknya. Mahasiswa semester akhir itu tinggal seorang diri di kamar kosnya, walaupun sebenarnya dia bisa saja manumpang di rumah pakde atau budenya. “Biar bisa mandiri,” begitu katanya. Selain sibuk sebagai asisten dosen, wanita berjilbab itu memberikan les privat Bahasa Inggris kepada anak-anak di sekitar tempat kosnya.
Aku mengenalnya karena hampir setiap dua minggu sekali Mbak Kinan datang ke sekolahku, melatih anak-anak teater. Kebetulan aku tergabung di komunitas itu. Ia juga sering membantuku menyelesaikan tugas-tugas Bahasa Inggrisku. Dia tak pernah menolak mendengar keluh kesahku. Berbeda sekali dengan Mama, yang tegas dan keras, Mbak Kinan selalu menghadapiku dengan penuh kesabaran. Dia tidak pernah memaksakan pikiran-pikirannya kepadaku. Ia hanya memberikan gambaran mana yang sebaiknya aku lakukan dan tidak aku lakukan. Semua selalu dikembalikan lagi kepadaku. Tidak seperti Mama, yang selalu merasa setiap keputusan yang lahir dari pikirannya adalah sebuah kebenaran yang tak bisa ditawar-tawar. Mama tidak pernah memberikan ruang bagiku untuk menikmati duniaku. Aku merasa terpasung oleh sikap otoriternya. Senja masih menyisakan merah di cakrawala di balik atap-atap bagunan rumah bertingkat. Sesaat berubah keunguan sebelum akhirnya menggelap. Di langit, tampak dewi malam merangkak perlahan muncul dari balik ranting-ranting pepohonan. Sebuah “ritus” pergantian waktu yang memesonakan. Angin menerbangkan suara adzan dari menara-menara masjid. Maghrib. Mengembara. Membawa seruan yang sempurna. Aku masih duduk memandangi langit, yang kini telah berubah kehitaman, dari balik jendela. Martabak telor pemberian Mbak Kinan masih utuh, belum kusentuh. “Mau shalat sama-sama?” tanya Mbak Kinan seraya menggelar tikar sajadah. Aku mengangguk. Bik Nah membukakan pintu rumah. “Mama udah tidur, Bi?” tanyaku setengah berbisik. “Ndak tahu, Non,” jawabnya sambil menutup pintu. Aku berjalan berjingkat-jingkat saat lewat di depan kamar tidur Mama. Takut ketahuan. Tadi minta ijinnya cuma sampai jam 9. Sekarang sudah hampir tengah malam. Mana tadi pakai acara bohong segala lagi… Aku bilang sama Mama mau mengerjakan tugas dari sekolah di rumah Afifa, teman sebangkuku.
Padahal, aku pergi ke bioskop sama Diko, kakak kelasku. Mama tidak akan mungkin mengijinkan aku keluar kalau aku katakan yang sebenarnya. Dia tidak suka aku jalan sama Diko. Bukan baru kali ini Mama melarangku berhubungan dengan teman cowok. Dia merasa, aku terlalu kencur untuk mengenal cinta, padahal aku sedah kelas 2 SMU. Aku membuka daun pintu kamarku. Perlahan. Tanpa suara. Kutekan saklar lampu kamarku ke posisi on. Neon 20 watt menyala. Dan… “Mama…?!” Mau copot jantungku waktu kulihat Mama ada di dalam kamarku. “Dari mana saja kamu? Kenapa jam segini baru pulang?” Nada bicaranya datar. Namun menggetarkan. Detak jantungku mulai tak beraturan. “Kan aku sudah bilang sama Mama, ak…” “Belajar di rumah Afifa, begitu?” Mama memotong. “Sejak kapan kamu pandai berbohong?” “A… aku…” “Tadi Mama nelepon ke rumah Afifa. Kamu tak ada di sana. Belajar…? Kamu pergi dengan pemuda itu, kan?!” Aku merunduk. Tak berani menatap mata Mama, yang berkobaran api amarah. “Kenapa kamu bohongi Mama?!” suaranya meninggi. “Mama sudah bilang, jauhi pemuda itu!” “Ta… tapi, Ma…” “Tak ada tawar-menawar!” “Kenapa sih Mama selalu melarang aku bergaul dengan teman cowok?” “Semua demi kebaikan kamu. Mama nggak mau kamu menelantarkan pelajaran kamu hanya demi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kamu masih terlalu kecil untuk itu.” “Selalu. Mama selalu manganggap aku anak kecil. Aku sudah kelas 2 SMU, Ma!” “Memangnya, kalau sudah kelas 2 SMU, kamu sudah merasa sangat dewasa, begitu?” “Ya nggak, tapi aku…” “Cukup!” bentak Mama. “Jangan membantah lagi!” “Mama nggak adil!” “Tahu apa kamu tentang keadilan?” “Kalau sikap Mama seperti ini, aku bisa jadi perawan tua, Ma. Aku nggak mau menghabiskan masa tuaku tanpa seorang pendamping, seperti Mama!” “Plak…” Mama melayangkan telapak tangannya ke wajahku. Belum pernah Mama melakukan sebelumnya.
Ia membalik tubuhnya. Melangkah tergesa-gesa meninggalkan kamarku. Masih sempat kulihat air menggenang di bening matanya. Aku berdiri terpaku. Tubuhku bergetar. Dadaku berdebar hebat. Aku merasakan nyeri. Bukan hanya di pipi. Terasa lebih sakit di hati. Malam itu merupakan puncak pertengkaranku dengan Mama. Aku sudah tak bisa lagi mentolerir sikap kerasnya. Aku sudah mengambil keputusan. Aku harus meninggalkan rumah ini! Hampir setengah dua saat kuketuk pintu kamar kos Mbak Kinan. Aku tak tahu harus pergi ke mana. Hanya tempat ini yang ada di kepala. Sampai beberapa saat lamanya aku menunggu, akhirnya Mbak Kinan membukakan pintu. “Mbak…” Aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Kutumpahkan seluruh tangisku di dadanya. “Ada apa? Kenapa kamu malam-malam datang ke tempatku sambil menangis seperti ini?” ujarnya. Ia membimbing aku ke dalam kamar. Mengambil gelas kosong lalu mengisinya dengan air mineral dari dispenser di pojok kamarnya. Diberikan kepadaku. Aku menerima gelas dari tangannya. Mereguk isinya sampai tinggal setengah. “Aku nggak mengerti dengan sikap mamaku, Mbak,” kataku setelah mampu menenangkan diri. “Kenapa dengan mamamu?” “Dia selalu menghalangi aku untuk memiliki teman cowok. Dia nggak pernah membiarkan aku menikmati duniaku. Aku kan sudah remaja, Mbak. Aku juga ingin merasakan memiliki teman cowok yang bisa diajak berbagi. Aku juga ingin merasakan cinta.” Mbak Kinan membelai rambutku dengan jemarinya. Kelembutan itu yang tak pernah diperlihatkan Mama kepadaku. Aku begitu merindukan kelembutannya. Membelai kepalaku seperti yang sering Mbak Kinan lakukan setiap kali aku membutuhkan dukungan. “Aku bisa mengerti perasaan kamu. Tapi aku juga memahami sikap mamamu.” “Kenapa begitu, Mbak?” “Di zaman yang serba bebas ini, orang-orang muda seperti kita sering kali gagal mendefinisikan cinta.
Sadar atau tidak, kita sering mempertuhankan cinta. Kalau sudah begitu, kita rela melakukan apa pun demi cinta. Bahkan sampai… kamu pasti tahu maksudku.” “Tapi aku nggak seperti itu, Mbak.” “Aku percaya. Mamamu pun pasti juga percaya padamu.” “Mama nggak pernah bisa mempercayai aku, Mbak. Buktinya…” Mbak Kinan hanya tersenyum membelai kepalaku. Rembulan surup di jurang jelaga. Malam merayap menapaki dinding-dinding udara yang mulai terasa dingin dibawa angin mengembara ke dalam kamar kos Mbak Kinan. Seseorang muncul dari balik pintu kamar Mbak Kinan. “Kinan, ada telepon buat kamu.” Tik-tik-tik-tik… Suara gerimis jatuh di atap rumah. Sebentar kemudian menderas. Mbak Kinan menyelesaikan wiridnya. Ia melepas mukena, memutar badannya ke arahku yang duduk di belakangnya. Kami berhadap-hadapan. “Aku punya sebuah cerita. Kamu mau mendengarnya?” katanya. Aku mengangguk. “Cerita ini terjadi sekitar tujuh belas tahun lampau.” Ia memulai cerita. “Ketika itu ada seorang pemuda kaya yang jatuh cinta kepada seorang gadis cantik kembang desa. Mereka bersekolah di tempat yang sama. Rupanya si gadis juga menyimpan hati kepadanya. Dan cinta pun diikrarkan. Mereka bagaikan sepasang merpati yang selalu terbang bersama-sama. Hampir tak terpisahkan. Sampai suatu ketika, nafsu yang bersembunyi di balik ikatan cinta mereka mengubah wajahnya menjadi begitu memesona. Akhirnya, atas nama cinta, gadis remaja itu rela menyerahkan miliknya yang paling berharga. Mahkota itu ia berikan kepada kekasihnya! Akibatnya… kamu pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya…” “Gadis itu mengandung?” “Ya.” “Lalu kekasihnya?” “Pemuda kaya itu pergi entah ke mana. Menghilang!” “Cowok sialan! Lalu apa yang terjadi dengan gadis itu?” “Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ayahnya mengusir dirinya.” “Tega betul orangtuanya.” “Begitulah.
Bersama janin yang ada di dalam rahimnya, gadis itu pergi meninggalkan rumah. Padahal waktu itu usianya belum genap delapan belas tahun! Sekolahnya berantakan. Hidupnya kacau balau. Di tengah trauma yang dialaminya, dia melahirkan anaknya. Seorang bayi perempuan!” “Perempuan?” “Bayi perempuan yang kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik.” Saat mengatakan itu, matanya ia lekatkan ke wajahku. Seolah ingin mengucapkan sesuatu. “Mbak…” Aku mulai menangkap arah ceritanya. “Dan gadis perempuannya itu, saat ini, sedang duduk di hadapanku.” Matanya berkaca-kaca. “Mama…?” Kabut berpendaran di bola mataku. Siap meledakkan tangis. “Kemarin malam, mamamu menelepon Mbak, dan menceritakan segalanya sambil terisak. Dia takut kehilangan kamu.” Mendengar penjelasan Mbak Kinan, aku tak mampu lagi membendung tanggul mataku. Kristal-kristal bening menetes, menderas, menganak sungai di kedua belah pipiku. Setangkup sesal menyelinap ke dalam kalbu. Aku sudah menyakiti hati wanita yang sekian lama memeram luka di hatinya. Tangisku pun meledak. “Mbak… Aa.. aku mau bertemu Mama…” Di luar, hujan turun amat deras. Bagai benang-benang perak yang dijatuhkan Tuhan dari ketinggian langitnya. Terdengar suara pintu kamar diketuk. Mbak Kinan beranjak bergegas membukakan pintu. Daun pintu terkuak lebar. Seraut wajah cantik milik seorang wanita berjilbab berdiri di muka pintu. Seluruh tubuhnya kuyup diguyur hujan. Wajahnya pucat. Kedua matanya sembab. Wanita itu menangis. “Ela...” katanya menyebutkan namaku. Lirih. “Mama…!” Aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Mama mendekap tubuhku erat. Dia menciumi wajahku sambil menangis terisak. “Maafkan Ela, Ma?” “Tidak, Sayang. Mama yang seharusnya minta maaf, karena telah melibatkan kamu ke dalam masa lalu Mama.” Oh, Mama… di hatimu ada telaga. Dan di telapak kakimu ada surga.



















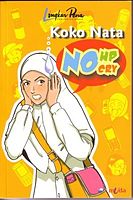
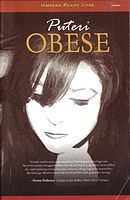
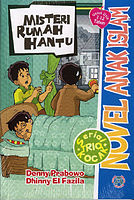


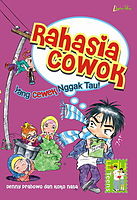


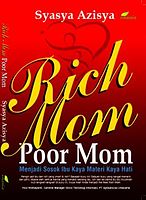



0 komentar:
Posting Komentar