Titin Baridin
In CERPEN, In Fiksi Dewasa, In Riza AlmanfaluthiSenin, 16 Maret 2009
Cerpen Riza Almanfaluthi
“Brak!” suara berat dari pintu lapuk yang didorong paksa terdengar. Begitu nyaring bagi si pemuda bermuka pucat yang sedang duduk di sudut dipan dengan memeluk kedua kakinya rapat-rapat. Mukanya hampir-hampir menelan lahap lututnya. Sarung yang menggulung dirinya tak mampu membuatnya terpisahkan dari dunia nyata. Buktinya ia masih saja mendengar suara pintu itu. Pula suara dari janda tua yang telah renta dengan bau tanah yang cukup menyengat. Miminya.
“Baridin! Baridin! Sudah tiga hari kau masih saja melamun. Apa sih Cung yang kau pikirkan?” Miminya bertanya sambil menengok ke sekeliling ruangan kamar yang begitu berantakan, gelap, dan suram. Sesuram keduanya yang masih saja terjerat dengan kemiskinan absolut sejak bapaknya Baridin yang juragan beras kaya raya jatuh bangkrut sepuluh tahun lalu gara-gara ditipu teman bisnisnya. Setelah itu, bapaknya Baridin mati mengenaskan dengan perut membuncit, darah segar keluar dari mulutnya yang terbuka menganga, mata melotot mendelik ke atas. Bisik-bisik tetangga mampir ke telinga mereka, bapaknya Baridin mati disantet musuhnya.
Kehidupan berubah seratus delapan puluh derajat. Rumah mewahnya dijual. Sawah, pekarangan pun mengalami nasib yang sama. Emasnya digadaikan yang pada akhirnya tak sanggup untuk ditebus. Dari hasil gadaian itu sebagian untuk menutupi semua hutangnya. Sebagian lainnya dibelikan gubug reot yang berada di sisi kuburan seberang kali.
Miminya cuma menjadi tukang cuci. Ia, Baridin, dengan keterpaksaan hanya sanggup jadi kuli panggul di pasar desa. Ia menerima nasib yang digariskan di telapak tangannya. Walaupun awalnya ia tak mau meminggul nasib itu. Tapi apa boleh buat perutnya tidak sanggup untuk bertahan menahan lapar. Sejak saat itu pula Baridin menyendiri bahkan pada miminya. Tertutup dari dunia pergaulan dengan pemuda-pemuda sebayanya. Setiap hari bangun pagi, pergi ke pasar, siang pulang, lalu tidur.
“Cung, ayo kerja sana, beras kita sudah mau habis,” miminya berkata sambil meletakkan piring seng berisi bubur di dekatnya. Tidak ada jawaban. Wanita tua itu cuma menghela nafas dan segera keluar dari kamar.
“Baridin mau kawin, Mi.”
Langkah wanita itu terhenti. Segera ia menoleh saat mendengar suara yang baru didengarnya lagi sejak tiga hari lalu itu. Terlihat wajah anaknya mendongak menatap dirinya. Ada selubung harap memenuhi wajahnya yang menghitam terbakar merah matahari. Kembali miminya duduk di sudut lain dari dipan itu.
“Dengan siapa?” hanya itu yang terlintas dalam pikirannya untuk menjadi sebuah awal dari rerimbunan pertanyaannya.
“Titin.”
“Anak Juragan Saeni itu?” tanyanya lagi sambil membayangkan raut wajah gadis yang menjadi kembang desa. Terlihat gerakan kepala ke bawah berulangkali dari anaknya, mengiyakan.
“Mimi cepat saja melamarnya, sekarang juga,” sebuah permintaan yang menyentak.
“Apa Baridin enggak mikir kita ini siapa? Juragan Saeni itu siapa? Juragan tanah, Baridin, juragan tanah. Kita cuma debu bahkan kotoran untuk keluarga mereka.”
“Tidak, pokoknya Mimi lamar dulu saja sekarang. Baridin sudah tidak tahan dengan semuanya.” Baridin tahu dirinya sedang dalam puncak kerinduan. Kerinduan yang ia tahan-tahan selama sebulan ini. Kerinduan yang muncul sejak pertama kali ia melihat sosok perempuan yang teramat cantik bagi dirinya. Menggoda naluri kelaki-lakiannya. Sangat, sangat menggoda.
“Kang, siapa tuh Kang? tanyanya pada Talib, seniornya. Yang ditanya sampai kaget karena biasanya anak ini tidak berkata sepatah katapun kalau memang tidak perlu untuk dirinya berkata pada dunia. “Itu Titin, anak orang paling kaya di desa ini. Dia baru saja datang dari Dermayu ikut ibunya, sekarang ia kembali ke bapaknya. Semua istri muda juragan pelit itu tidak bisa punya anak.”
Berhari-hari Baridin cuma bisa memandang Titin dari kejauhan. Ada sebongkah rasa melesak dari dasar jurang hatinya. Dengan harapan yang semakin melangit. Dan ia terpaksa jatuh ke lembah kenelangsaan tiada berdasar saat tiga hari lalu itu ia menyapa TItin.
“Nok Titin, ayu temen sira Nok.”
Yang diterimanya hanyalah pandangan jijik, “cuih…!”. Lesatan air kental keluar dari mulut Titin. Tidak ke muka Baridin yang setengahnya berwarna merah karena tanda lahir, tapi ke tanah. Tapi itu sudah cukup dimengerti Baridin. Ia mundur. Tapi tetap dengan lenguhan, “Nok Titin, ayu temen sira Nok.”
Nelangsa yang menjadi sengsara. Mengurung diri di kamar tak berjendela, tiga hari tak ke pasar membuatnya semakin menderita. Mulutnya terkunci kepada siapa-siapa. Bahkan sebongkah otak di kepalanya tidak sanggup untuk memikirkan yang lain, cuma Titin satu-satunya.
“Baridin tidak kasihan sama Mimi? Isin cung…isin,” pipi miminya terlihat menganak sungai dengan air mata. “Kita itu orang belih gableg. Seharusnya tak perlu mikir macam-macam. Duitnya mana lagi buat lamaran.”
“Sarung Baridin saja,” setelah itu Baridin tidak berkata-kata lagi. Kembali ia mengurung dirinya di balik sarung. Ia nyaman di sana, karena itu hanya dunia satu-satunya yang dimilikinya.
*
Persangkaannya tepat. Lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Juragan Saeni. Sarung anaknya yang dijadikan barang seserahan dilempar ke kakinya. “Berkaca Bu. Tidak pantas untuk si Titin. Terus mau dikasih makan apa si Titin? Kalau saja suamimu masih hidup saya pasti akan menertawakannya. Najis!”
“Anakmu jelek minta ampun,” ucap Titin meningkahi.
Sang mimi pulang dengan membawa kehinaan. Herannya ia mau-mau saja memenuhi permintaan Baridin untuk melamar Titin. Tapi ia tak tega melihat kondisi anaknya yang sudah sepekan ini berpesta dengan kesenyapan.
Baridin hanya diam mendengar semua cerita miminya. Isak tangisnya menjadi soundtrack yang memilukan. Tiba-tiba Baridin bangkit. Segera ia makan dengan lahap bubur yang sedari pagi ia belum sentuh. Lalu tanpa menengok pada miminya ia pergi begitu saja dengan sarungnya yang tak sempat terberikan pada pujaan hati.
“Baridin! Baridin! Kemana kau Cung?” teriak sang mimi. Tidak terjawab. Cuma lenguhan, “Nok Titin, ayu temen sira Nok.”
Baridin bergegas pergi ke sebuah bangunan tua jauh dari desanya. Di dalamnya terdapat Makam Ki Buyut Leluhur. Ada makam-makam lainnya yang terletak di luar. Beringin besar dan kokoh menjadi kanopi yang melindungi komplek makam kecil itu dari terpaan sinar matahari.
Baridin berniat untuk menuntaskan tekadnya agar tidak sekadar menjadi lenguhan tapi memiliki sepenuhnya diri Titin. Untuk itu ia akan puasa tiga hari tiga malam. Tanpa makan tanpa minum. Sebelumnya ia mandi di sungai kecil di belakang. Cukup dengan kembang pohon mangga yang berjatuhan di pinggir kali sebagai syarat ritualnya.
Lalu tepat jam satu malam, sambil menghadap ke arah rumah Titin dan membayangkan wajahnya ia berucap mantera:
Teka idep, teka madep. Teka pangleng, teka puyeng, teka welas, teka asih. Laking pangkon ingsun. Duduh ngejok-ngejok bumi. Ngejok hatine Titin. Nyen lagi turu. Gageh Tangiah. Nyen wis tangi, madep maring badan ingsun.
Baridin gemetar. Jaran guyang pun berputar. Sangat ritmis. Seirama dengan Titin yang tiba-tiba terbangun dari tidur. “Arghhhhh…” teriak Titin gemetar. Tubuhnya basah dengan keringat dingin. Dalam mimpi tubuhnya limbung terseret putaran arus deras air sungai. Tangannya menggapai-gapai permukaan. Tapi ia tak sanggup untuk melawan. Semakin menjauh dan tenggelam. Ada tarikan kuat dari dasarnya.
Keesokan pagi, seisi rumah Juragan Saeni heboh. Titin tidak terbangun dari ranjangnya. Bukan karena tak mau tapi ia tak sanggup. Tubuhnya lemas lunglai. Wajahnya pucat. Dari mulutnya terdengar ceracau tidak jelas, tapi sempat terucap nama seseorang. Ceracau itu berhenti saat maghrib jelang. Cukup memberikan waktu kepada penghuni rumah itu untuk beristirahat menjaga Titin.
Tapi, jam satu malam, kembali Titin tersentak. Terbangun duduk. Gemetar. Ia meningkahi suara Tokek yang terdengar satu-satu.
“Tokek!” suara pertama dari reptil itu membahana.
“Kang Baridin ganteng.”
“Tokek!”
“Kang Baridin sayang.”
“Tokek!”
“Tunggu Nok, Kang!”
Paginya, seiisi rumah terkejut karena Titin sanggup untuk bangun. Tapi bangun hanya untuk mondar mandir antara dapur dan teras rumahnya yang besar. Kadang berjalan pelan, kadang setengah berlari. Mulutnya tetap menyeracau. Dukun yang datang ke rumah mereka memastikan Titin kena gendam yang amat kuat.
Pada malam yang ketiga. Titin kembali terbangun dengan gemetar. Tidak lagi duduk. Kini ia langsung bangkit dengan mata terbuka lebar.. Salah satu kakinya menjejak-jejakan tanah seperti kuda betina yang sedang birahi. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar suara ringkikan. Panjang.
“Kang Baridin…! Kang Baridiiiiiin….!” teriaknya kencang. Ia tendang pintu kamar kuat-kuat. Beberapa orang yang berusaha untuk menenangkan dirinya tak mampu untuk menahan kekuatan dahsyat yang ada pada diri Titin. Ia bagaikan banteng ketaton. Meronta, memukul, dan menendang kesana-kemari. Lalu ia berhasil lari keluar rumah menerobos gelapnya malam. “Kang Baridin, tunggu Nok Titin, Kang!” teriaknya. Sambil meringkik.
Satu desa geger. Semalaman tidur mereka terganggu. Jalanan dipenuhi tawa mengerikan dan sedu sedan menyayat menuju batas desa. Desa sebelah pun geger. Ada perempuan baru meringkik terus menerus menuju ujung desa ditingkahi lengkingan yang samar, “Kang Baridin, Nok Titin sayang sama Kakang.”
Desa sebelahnya lagi geger pula. Berita tentang perempuan yang tetap dengan ceracauannya, tetap dengan ringkikannya, lebih dulu sampai ke warga desa daripada raga Titin. Bahkan beritanya menjadi lebih dahsyat, perempuan berwajah kuda. Mereka berbaris di pinggir jalan hanya untuk melihat tingkah gadis desa yang dulunya terkenal kemana-mana karena kecantikannya yang luar biasa itu.
Tapi mereka kecewa saat melihat Titin datang. Pengharapan mereka melihat sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan tak terwujud. Muka Titin tidak muka kuda, tapi suara yang keluar dari mulutnya itulah yang mirip kuda.
Titin tetap berlari. Meringkik. Menyeracau. Dan mereka mengikuti Titin sampai ujung desa. Tiba-tiba Titin berhenti. Warga pun ikut berhenti, menunggu apa yang akan dilakukan olehnya. Titin berbelok ke kanan melalui jalan setapak penuh belukar. Kini warga urung mengikutinya, karena tahu Titin sedang menuju ke komplek makam angker. Tak ada yang berani ke sana selama bertahun-tahun.
“Kang Baridin...!” teriak Titin sambil meraup tubuh pemuda yang tergeletak lemah di sudut bangunan makam. Masih ada nafas satu-satu. Matanya membuka. Menatap Titin lekat-lekat. Ia menguatkan diri untuk berkata: “Nok Titin ayu temen sira Nok.”
“Kang Baridin, Titin cinta sama Kang Baridin. Titin rindu. Titin mau dikawin sama Kang Baridin. Titin tidak mau ditinggal Kakang. Titin sayaaaaaaaang sekali sama Kang Baridin,” suaranya keluar tak mampu berhenti, tapi kini dengan tangis dan tawa yang meledak bergantian.
Baridin tersenyum. Ringkikan Titin seperti nyanyian merdu ditelinganya. Mati pun ia tak penasaran, walaupun bayang-bayang neraka sudah memberatkan mata . Dan Izrail sudah marah hendak merenggut sisa-sisa kehidupannya. Bahkan saat Juragan Saeni datang mendekat menghunjamkan keris di dadanya, Baridin tersenyum. Tapi senyum itu bagi Juragan Saeni adalah seringai bapaknya Baridin yang ia santet dulu. Bengis penuh kemenangan.
*
Keterangan Bahasa Cirebon:
Cung : Panggilan kepada anak laki-laki
Nok : Panggilan kepada gadis/anak perempuan
Mimi : Ibu
Temen : sekali/sangat
Belih gableg : Tidak berpunya
Isin : Malu
Dedaunan di Ranting Cemara
Pabuaran, 26 Juli 2007
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



















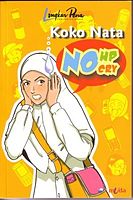
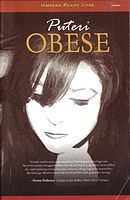
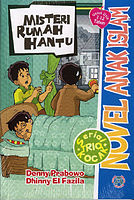


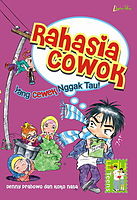


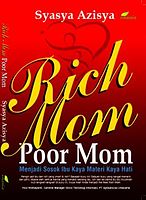



0 komentar:
Posting Komentar