Cerpen koko Nata
Sriwijaya Post, edisi 03/02/2003
Anak itu lucu. Lebih lucu daripada teddy bear atau boneka mana pun yang dipajang pada toko etalase mainan. Pipinya montok seperti bakpao panas. Matanya hitam berkilau bagai mutiara dari lautan. Dan bibirnya, merah jambu bercahaya. Bila ia tersenyum, sempurna sudah karunia Tuhan yang dianugrahkan kepadanya. Aku suka anak itu.
Usianya tak lebih dari tengah tahun pertama. Aku sering melihatnya ditimang-timang tiap petang dijalan depan rumah. Demi melihat tawanya, bertingkahlah orang-orang dengan ekspresi kanak-kanak. Jika menarik merekalah bibirnya yang selalu basah. Kata-kata kerap mengajak bayi itu berbicara. Padahal semua orang tahu, satu kalimatpun ia tak punya tapi orang tetap senang mengajaknya bicara, sebab ia lucu, lugu, segar bagai embun pagi. Sebenarnya aku ingin mendekatinya, menggendongnya serta memberikan satu kecupan. Aku ingin menimang dan menyanyikan lagu sayang. Biar sumbang, ia tak akan menentang. Ia hanya akan menangis atau tertawa sebagai tanda suka tidaknya. Sayangnya aku tak bisa. Aku tak bisa menghampiri atau bahkan memeluknya. Ia bagai bintang yang tak dapat dijangkau. Ia seperti sinar suci yang pecah saat kujamah. Ia...ah...mengapa jauh jarak terbentang kalau aku merindukannya. Inikah dera yang harus kuterima akibat perilaku masa lalu? Aku terpenjara oleh jeruji yang aku dirikan sendiri. Aku tenggelam dalam lautan penyesalan. Aku...Aku harus puas hanya dengan menikmatinya dari sela-sela jendela. Aku telah tersihir oleh kerling lembut pesonanya tapi tak berdaya.***
Beberapa bulan yang lalu aku tak acuh dengan percakapan itu “Stt... anaknya Nuning sudah lahir” “Anak haram itu” “Iya...” “Bakalan ngetop lagi kampung kita” “Betul. Kelahiran anaknya ini pasti lebih ramai dibanding peristiwa perkosaannya.” “Lagian, mau-maunya dia mengandung benih lelaki yang tak jelas asal muasalnya” “Ya namanya juga musibah, Bu, siapa, sih yang mau” “Tapi, kan, dia bisa saja menggugurkan kandungannya” “Ibu nggak tahu sama si Nuning, sih. Nyamuk saja enggan dia bunuh apalagi janin dalam rahimnya. Dia memang sempat bilang, anak itu tidak dikehendakinya. Tapi setelah perutnya membesar dia malah jadi sayang. Dia menganggap musibah sebagai takdir, cobaan, cara yang di atas mengasihinya. Siapa tahu anak itu malah membawa berkah” “Ce...ile...masih sempat ceramah juga dia rupanya.” “Biarlah, Bu. Selama tidak merugikan kita. Ya nggak massya... lah” “Betul...betul... Ngapain kita pusing mikiran dia. Dianya sendiri tenang-tenang saja” “Iya” “Lebih baik kita mempersiapkan diri. Sekarang kan banyak wartawan yang ingin meliput kejadian ini. Nah kita sebagai tetangganya pasti ikut dimintai keterangan. Kita jadi masuk koran deh. Ikutan ngetop. Siapa tahu ada yang tertarik untuk mengorbitkan kita jadi model” “Hi...hi...hi...ibu ini ada-ada saja”***
Dengan mata kulumat habis sosok perempuan itu. Ia tak bisa dikatakan cantik tapi salah jika menilainya tak menarik. Ia punya pesona yang tak bisa diraba dengan indra. Apa namanya, aku tak tahu.Ia perempuan yang hebat menurutku. Ia tak menyesal dengan segala sial yang menghampiri. Ia tak menganggap Tuhan tak berlaku adil padanya. Tabah dan sabar adalah teman yang membuatnya tegar menghadapi bisik-bisik pedas gunjingan. Semua ia jalani dalam syukur baik suka maupun duka. Dia yakin dibalik cobaan maupun musibah pasti tersirat hikmah. “Aduh lagi mamam, ya? Mamam apa, cayang?“ seorang perempuan tambun setengah baya menegur anaknya. Dia tersenyum seraya menyodorkan sesendok bubur untuk buah hatinya. Aku ingin bertanya bubur apa yang engkau suapkan? Makanan penuh gizi atau sekedar beras yang direbus dengan air berlebih? Susu yang bagaimana pula kau regukkan untuk melepas dahaga bayimu? ASI kaya sempurna atau sekedar air putih encer tiada guna. Aku yakin jawabannya pasti mengecewakan. Kau hanya seorang yatim yang kini bukan janda dan bukan seorang istri pula. Rumah kayu yang berdiri di samping kediamanku sudah cukup menggambarkan keseharian. Bila mengingatnya aku jadi benci sebenci bencinya pada lelaki yang tega menghinakannya. Mengapa ia dan harus ia. Bukankah masih banyak gadis kaya bergaya foya-foya dan hura-hura. Kenapa tidak mereka saja yang jelas hidup tanpa punya arah. Kenapa harus Dia ? Semakin memikirkannya semakin gila saja otakku dijejali tanya dan terka. Penyesalan bereaksi hebat dengan kagum yang datang. Hari kemarin senantiasa menjadi senjata yang meneteskan nestapa. Dan aku semakin benci dengan laki-laki itu.***
“Kau jadi milikku malam ini!” “Tidak..tidak...jangan... !!” “Telah lama kau bercokol dalam alam maya. Sudah lelah dahaga menunggu rengkuh cinta. Mari kita puaskan mari kita tuntaskan sekarang juga.” “Jangan...kau hanya akan menikmati neraka lebih segera. Aku bukan kembang kau bukan kumbang. Hentikan...” “Tidak...aku tak bisa berhenti.” “Tolong jangan buat Tuhan dan pengikutnya mengutuk perbuatanmu!” “Hehehe... Mari kita mulai saja.” “Jangan... Pergi!” “Ayolah!” “Tidak!” “Ayo!” “Tidak!!!” Breeet... “Aaaa...” Aku terjaga. Aku melihatnya. Lelaki yang kubenci dengan perempuan itu.***
Pelangi melengkung di langit biru. Harum semerbak bunga menebar bau. Alam di mata berwarna-warna indah mempesona. “Bimbii...Bimbi...ayo sini ikut papa...” Tawa renyah bocah tak berdosa. Riang jenaka anak manusia memulai perjalanannya. “Sudah lama papa ingin menggendongmu Bimbi. Ayo...kemarilah, Sayang!” Anak manis merentangkan tangan. Dekap bahagia akan segera diberikan. “Duh, manisnya. Kua benar-benar anugerah terindah meski tak pernah sengaja terencana.” Wajah polos lebarkan bibirnya. Liur menetes basah berpola peta. “Senangnya bisa menggendongmu...” Tanpa diduga si bocah berubah. Badan menghitam tumbuhkan bulu serigala. Taring runcing mencuat siap mengoyak mangsa bersama dengus panas moncong mencari udara. Anak manis menjelma monster buruk rupa. Ia siap menerkam. Menghisap darah. Mencabik tubuh hingga patah tulang jadinya. “Mengapa...mengapa kau jadi begini...” “Grrr..Graw...” Tiada jawaban. Hanya kengerian yang disajikan.Kuku tajam mencakar sasaran. Kulit tersayat. Darah membasah. Anak buruk lepas dari pegangan. “Bimbi...Bimbi... ini papa... ini papa...” “Graw..Graw...” Luka mengaga. Jerit membahana. Malam pecah porak poranda “Tidak...” Aku berteriak. Mimpi ternyata. Napasku turun naik memasok udara. Keringat bergulir bergilir-gilir. Aku sudah tak dapat menghitung lagi sudah berapa kali kengerian itu menghantuiku. Bayang-bayang menakutkan seolah tiada lelah bergentayangan. Aku ketakutan. Aku tertekan.***
Untuk kesekian kalinya aku kembali mengamati anak dan ibu tetanggaku. Wajah mereka masih sama. Masih ceria tertawa renyah. Hidup dibiarkan berjalan apa adanya. Yang terjadi terjadilah. Mereka tak peduli dengan suara-suara usil yang melingkupi.
Sedang aku, lihatlah aku. Makin ringkih menapaki hari makin tersiksa oleh nyeri tersembunyi. Panah-panah maya terus melesat ke arahku. Sebuah kekuatan memaksa dan terus memaksa agar aku mengaku bahwa akulah ayah bayi itu.***
Palembang, 6 September 2002



















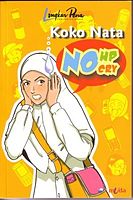
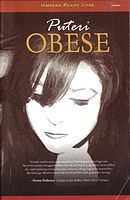
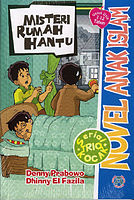


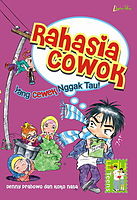


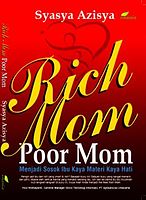



0 komentar:
Posting Komentar