“Mudah-mudahan Rani suka dengan sepatu dan tas ini, biar tambah semangat sekolahnya.”
“Awas!.....” Bruk!
“Aduh! Kepalaku, mengapa sakit sekali? Perutku. Darah. Tidak! Ya Tuhan, Anakku”
***
Mendung masih asyik bergelayutan, ragu untuk menumpahkan persediaan airnya ke bumi, di pagi 28 Februari. Gorden putih menari-nari kecil tertiup semilir angin yang dengan gemulai masuk ke kamar ini. Kamar yang sudah dua puluh enam tahun kutempati, menjadi persinggahan saat ingin menyepi, melepaskan segala letih dan penat. Kutatap pantulan diri di cermin, inilah muka di umur dua puluh delapan tahun, krim wajah apapun yang dipakai tidak bisa menghilangkan kerutan-kerutan halus di sekitar mataku. Inilah aku, yang sesekali masih disebut Ibu sebagai anak pelupa. Ya, sesekali, karena dulu Ibu selalu bilang kalau aku anak yang sangat pelupa. Sudah tiga dokter yang didatangi, mulai dari dokter umum, dokter syaraf sampai dokter kejiwaan. Ketiga dokter tetap pada kesimpulan yang sama bahwa tidak ada yang aneh pada badan, jiwa dan isi kepalaku. Namun, Ibu tidak puas dengan penjelasan mereka sehingga didatangi juga “orang pintar” yang katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ada beberapa kejadian yang masih kuingat pada saat bertemu dengan “orang pintar” itu, Mbah Tarjo namanya.
“Siapa yang sakit?”
“Anak saya Mbah.”
“Sakit apa?”
“Anu… Mbah, anak saya sering lupa.”
“Saya juga sering lupa, ini saya sudah sering beli kacamata gara-gara saya lupa taruhnya di mana.”
“Tapi… anu Mbah, anak saya ini puaarah banget lupanya. Masa’ dia lupa adiknya ditinggal di mana.”
“Maksudnya?”
“Begini Mbah, waktu itu saya sama anak ini dan adiknya ke pasar. Karena saya kasihan melihat mereka harus desak-desakan di dalam pasar maka saya titipkan ke tukang soto langganan saya. Eeeehhhhh, waktu saya kembali cuma ada dia disana. Terus kan saya tanya sama tukang sotonya, abang itu bilang kalau anak saya yang pelupa ini tadi jalan-jalan. Terus kan saya tanya sama anak ini, adik kamu mana? Dia cuma geleng-geleng kepala sambil bilang lupa. Saya sudah panik banget mbah, tahu kan sekarang ini banyak penculik anak apalagi ada yang dijadiin penge
“Iya, Bu…. Iya, Bu….. saya sudah mengerti.
Aku ingat jidat mbah Tarjo sedikit mengkerut mungkin dia heran bagaimana ada orang yang dapat cerita begitu banyak dan cepat hanya dalam satu tarikan napas.
“Nama kamu siapa, Nak?”
“Rani”
“Nama panjang?”
“Rani Trihapsari.”
“Kamu anak ketiga, ya?”
Ada nada sombong dan merasa hebat yang kutangkap dari pertanyaan itu, mungkin dia mengira bahwa tebakannya tepat.
“Begini Mbah, Rani memang anak ketiga, tetapi kedua kakaknya meninggal waktu dilahirkan dulu, katanya sih prematur gitu, Mbah. Jadi bagaimanapun saya dan suami tetap menganggap Rani ini anak kami ketiga dan adiknya kami beri nama Catur Aditya karena anak keempat.”
“Oh… baiklah.”
Saat itu mbah Tarjo sudah semakin pusing menghadapi Ibu yang suka sekali bercerita. Lalu dia pun memberikan tindakan yang sekiranya bisa menyembuhkan penyakit lupaku. Segelas air diminum dan pada tegukan terakhir, air itu tidak langsung ditelan melainkan dikumur-kumur lalu disemburkan tepat ke wajahku dan tangan kanannya diusapkan ke wajah yang terlanjur basah tadi sambil mulutnya komat-kamit. Kaget, kesal dan jijik sebenarnya aku diperlakukan seperti itu, tapi aku diam saja.
“Ini Nak Rani, saya kasih ramuan untuk menyembuhkan penyakit lupanya. Setiap malam Jum’at kliwon jam delapan taburkan ramuan ini dalam air dan mandilah dengan air tersebut.”
“Maaf Mbah, saya harus bayar berapa untuk semuanya ini ya?
Delikan mata tidak suka dari mbah Tarjo yang menghujam Ibu dan mulutnya yang merengut tidak bisa kulupa. Sepertinya dia tidak suka dipotong omongannya. Tapi yang membuatku geli adalah sikap cuek Ibu terhadap sikap Mbah Tarjo dan masih terus bicara.
“Bukan apa-apa mbah, uang saya pas-pasan.”
“Begini Bu, biaya konsultasi dua puluh ribu sedangkan ramuan ini harganya sembilan puluh sembilan ribu. Terserah Ibu mau bayar yang mana. Bayar untuk konsultasinya dulu, obatnya diambil besok-besok juga tidak apa-apa.
“Aduh bagaimana ya, saya hanya bawa dua puluh ribu. Ongkos pulang buat berdua sepuluh ribu. Udara panas terik begini, apa Mbah tega melihat kami pulang jalan kaki, dua puluh kilometer dari sini Mbah. Kasihan Mbah, apalagi Rani sudah kurus kecil, kena terik matahari tambah hitam saja anak ini.
“Baiklah baiklah… Ibu tidak usah bayar, gratis!”
“Wah terimakasih banyak Mbah.”
Ibu berbohong saat itu karena sebenarnya Ibu membawa uang lebih dari yang diminta mbah Tarjo. Pada saat aku tanyakan mengapa tidak membeli ramuan mbah Tarjo, Ibu hanya menjawab, “Ibu tidak suka anak ibu disembur dengan air kumuran mulut Mbah tadi, jorok. Ambil saputangan ini, bersihkan mukamu lagi” Ibu lalu membantuku menyeka muka yang sebenarnya sudah kering dengan saputangannya, sambil tetap mengomel. “Tadi ibu kira, mbah itu hanya akan memberi kamu obat-obatan herbal dan bukannya mengharuskan kamu mandi pada malam Jum’at kliwon, saran yang aneh.”
Pada saat itu tanpa malu dilihat banyak orang aku memeluk dan mencium pipi Ibu berkali-kali.
“Rani sayang Ibu”
“Kamu kenapa sih Rani?”
“Terimakasih ya bu, sudah sayang dan sabar membesarkan Rani. Rani sayang Ibu”
“Iya…iya… Ibu sayang sama Rani, sayang sama adikmu juga. Jadi jangan sampai lupa sama adikmu lagi ya.”
“Iya bu, Rani tidak akan lupa”
“Ayo, kita jalan, malu tuh diliatin sama orang-orang”
“Biarin, biar semua orang tahu kalau Rani sayang ibu”
Saat itu pasti Ibu salah tingkah dan risih dicium-cium pipinya. Pipi yang lima belas tahun kemudian masih terkena bibir jailku, pipi yang sudah banyak kerutan-kerutan dan flek hitam disana-sini.
Ibu memang kurang pandai menunjukan rasa sayangnya dengan kata, pelukan, ciuman. Tapi tidak perlu Ibu melakukan itu semua. Setiap hari Ibu bangun pagi menyiapkan sarapan untuk kami sekeluarga meskipun sudah ada Mbok Iyah yang siap melakukan tugas tersebut. Ibu selalu membuatkan makanan yang kami makan setiap hari. Ibu yang selalu membuatkan susu hangat bila aku harus bergadang karena mengerjakan tugas kuliah, bahkan berniat puasa untuk keberhasilanku mengahadapi sidang skripsi. Mata Ibu yang berbinar bangga melihat laporan IPK ku di setiap semester. Ibu yang selalu membuatkan pakaian yang akan kami kenakan setiap hari raya. Pernah aku protes ke Ayah mengapa kami sekeluarga harus mengenakan pakaian yang motifnya sama setiap hari raya. Namun lambat laun aku tidak mempersoalkan itu lagi, karena aku bahagia melihat muka Ibu yang berseri-seri gembira melihat kami berpakaian seragam, selain itu baju buatannya memang indah. Dan banyak hal lainnya yang sekarang aku sadari merupakan cara Ibu menyayangi kami sekeluarga.
Aku selalu rindu Ibu, sering aku memerhatikan Ibu bila kami sedang berdua. Saat mulutku hendak menceritakan segala hal tiba-tiba Ibu mengomeli adik, “Lihat kak Rani, pintar, sayang sama Ibu, sama Ayah, dan tidak rewel kalau disuruh makan. Kamu juga harus seperti kak Rani ya.” Aku hanya tersenyum getir melihat tingkah Ibu. Tidak hanya sampai situ perhatian berlebih terhadap adik, suatu waktu setiba dari kantor aku temukan Ibu tertidur di ruang tamu bukan menunggu aku tetapi adik yang katanya belum pulang.
Kami tidak berkutik bila Ibu sudah meminta sesuatu atas nama adikku. Pernah aku disuruh untuk membelikan bola basket karena menurutnya adikku sedang senang bermain basket, padahal bola sepak yang dibeli Ayah dua bulan lalu masih teronggok bersih tidak pernah dimainkan di pojok kamar. Ibu pun meminta Ayah membelikan play station 3 sebagai hadiah ulang tahun adik, sebenarnya Ayah tidak setuju tetapi Ibu tetap ngotot.
Tidak hanya kepadaku Ibu bercerita tentang semua tingkah laku adik, Ayah dan mbok Iyah tidak luput dari sasaran ibu. Ayah, meskipun aku tahu capek tapi bersedia mendengarkan cerita ibu. Ayah yang selalu mengelus lembut kepala ibu dan sering kulihat mata Ayah berkaca-kaca haru memperhatikan Ibu yang asyik bercerita. Tidak pernah aku melihat Ayah menghela napas tidak sabar, meskipun yang diceritakan Ibu terkadang hal yang sama. Mbok Iyah─sosok tua yang masih sehat dan kuat, telah ikut keluarga ini sejak Ayah dan Ibu menikah─ sambil memijat pundak Ibu, setia mendengarkan keluh kesahnya. Mungkin bagi ibu, Mbok Iyah adalah pengganti Ibu─nenekku─yang telah meninggal sebelum aku hadir.
Mbok Iyah yang mengetahui semua kejadian di keluarga ini, orang yang aku dan Ayah percayai untuk menemani Ibu bila kami tidak di rumah. Mbok Iyah tempatku curhat kalo sedang gundah menghadapi tingkah Ibu. Dulu sekali curhatku kepadanya kebanyakan tentang kekesalanku kepada Ibu yang sepertinya terlalu sering membicarakan dan memperhatikan adik. Kutaruh kepalaku dipangkuannya.
“Non Rani harus sabar dan mengerti kondisi ibu yang seperti itu.”
“Tapi sampai kapan Mbok? Semuanya pasti tentang anak itu, kesal aku Mbok”
“Jangan ngomong gitu non, ibu juga masih perhatiin non kan.”
“Iya sih Mbok tapi….”
“Ingat janji Non ke Ayah”
Janji, ya aku pernah berjanji ke Ayah dan Mbok Iyah yang selalu menjadi pengingat janji yang terjadi sebulan setelah Ibu melahirkan adik. Aku ingat saat itu Ayah memelukku sambil berucap “Ibu selalu sayang Rani, Rani harus janji untuk sayang Ibu juga, ya. Jangan buat Ibu sedih. Rani harus bikin Ibu bahagia, tersenyum”. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa tidak mungkin seorang anak berumur enam tahun sudah mengerti apa itu janji. Namun percayalah aku selalu berusaha membuat Ibu bahagia dan tersenyum.
Jam besar di ruang tamu berdentang delapan kali, biasanya saat ini aku sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan di kantor tapi khusus tanggal 28 Februari aku selalu minta ijin untuk tidak masuk bila hari itu adalah hari kerja, seperti sekarang.
“Rani, sudah siap? Kita berangkat sekarang?” Ketukan pintu dan panggilan Ayah menyadarkanku dari lamunan.
“Iya Ayah, Rani sudah siap.”
Cahaya matahari menyusup masuk agaknya hujan tidak jadi turun sekarang. Angin melayap membawa kumpulan awan mendung tadi ke tempat lain.
Seperti hari kerja di waktu pagi, jalanan dipadati oleh kendaraan bermotor dan mereka yang menunggu angkutan umum.
“Benar nih, Ayah tidak capek? Kemarin sampai rumah jam setengah satu, kan?”
“Sekarang Ayah yang nyetir, pulangnya biar kamu yang nyetir.”
Kutatap Ayah di sampingku yang menyetir tenang, tidak pernah aku melihat Ayah kesal oleh para pengguna jalan yang bertindak sembarangan, bahkan sangat jarang Ayah memanfaatkan klakson mobil ini. Entah, Tuhan ciptakan dari apa sosok yang kucintai ini sehingga menjadi Ayah yang setia, penyabar, penyayang dan pekerja keras. Segala sesuatunya akan dilakukan untuk membahagiakan Ibu dan aku. Mbok Iyah dan Ibu duduk berdekatan di kursi belakang, tidak terdengar suara mereka sejak meninggalkan rumah tadi.
***
“Tidak dimakan rotinya Bu?” Agaknya pertanyaanku mengagetkannya dan aku merasa ada yang aneh dari Ibu hari ini.
“Ibu belum lapar.”
Ya, ada yang aneh dari Ibu. Seminggu ini aku memang keluar kota dan sore kemarin aku tiba di rumah, tapi baru pagi ini aku jumpa Ibu. Tidak seperti biasa Ibu yang selalu ramai bercerita, Ibu pun tidak menanyakan tujuan kepergian pagi ini seperti yang biasa ditanyakannya setiap tahun.
“Non Rani mau makan rotinya sekarang?” Belum sempat aku bertanya lebih lanjut ke Ibu.
“Nggak Mbok, nanti saja. Ayah bagaimana?”
“Nanti saja, Ayah juga belum lapar.”
Sejam berlalu dan sekarang kami berada di tempat ini. Sambil merangkul pundak Ibu, Ayah berjalan mendahului aku dan Mbok Iyah memasuki pintu gerbangnya. Kami susuri jalan setapak yang membelah hamparan gundukan-gundukan tanah berumput hijau dengan batu-batu yang tertata rapi di setiap gundukannya. Ada danau kecil disana dengan bangku-bangku taman yang mengelilinginya. Tempat indah untuk menentramkan hati sedih mereka yang datang mengantarkan orang terkasih ke tempat peristirahatan terakhir. Kulihat Ibu membisikan sesuatu ke Ayah, dan dibalas dengan senyum dan ciuman lembut dikening Ibu. Kurasakan angin bertiup semilir dan hening menggelayut menambah syahdu suasana, tidak ada siapa-siapa di pemakaman ini, hanya kami. Mengapa tiba-tiba mata ini seperti danau yang sudah hampir meluap airnya.
Beberapa saat berjalan sampailah kami di tempat yang dituju, tempat dimana tiga makam dengan tiga nisan sebagai penanda tiga jiwa yang telah meninggalkan kami. Kudengar isakan tertahan Mbok Iyah, kulihat mata Ayah berkaca-kaca memerah dan sesekali diseka dengan telapak tangannya. Kuhela napas panjang agar tidak jatuh pula air mata ini. Dalam diam kami bersihkan ketiga makam ini.
Aku tidak tahu sejak kapan Ibu berada di sampingku ketika tiba-tiba tangannya memegang tanganku.
“Maaf… maafkan Ibu,” ujar Ibu lirih.
Kutatap wajah Ibu yang iba, lalu wajah Ayah yang tersenyum kecil dan mengangguk.
“Ibu sudah ingat.”
“Apa maksudnya, Yah?” Bingung, aku mencerna kata-kata Ayah sementara Ibu masih menggenggam tanganku.
“Ibu mulai ingat tentang keadaan Adit yang sebenarnya,” kembali Ayah mencoba menerangkan.
“Maafkan Ibu, Nak?” Berkaca-kaca mata Ibu ketika mengucapkan kata maaf itu.
Masih kutatap wajah ibu, ada rasa sesak didada. Kusentuh wajah ibu dengan kedua tangan ini yang bergemetar karena haru terkenang kejadian-kejadian lampau. Kucoba bersuara walau lirih yang keluar.
“Benarkah Bu, ibu sudah tahu di mana Adit?”
“Iya Nak, Ibu ingat.” Dengan tersekat Ibu berusaha menjawab pertanyaanku.
Tidak sanggup lagi kutahan air mata ini, kupeluk ibu dan kutumpahkan semua didalam pelukannya. Ibu tidak perlu minta maaf karena Ibu tidak salah, semua terjadi karena kehendak-Nya. Semakin erat kupeluk Ibu saat teringat perjuangan Ibu menjalani terapi dan semua obat yang harus diminum untuk kesembuhan fisik dan jiwanya. Kurasakan kedua tangannya hangat memeluk diriku, pelukan dari orang yang menjadi pengganti Ibu kandungku. Ibu kandung yang kembali ke Ilahi bersamaan dengan kelahiranku.
Aku memang tidak lahir dari rahim orang yang memelukku sekarang tetapi lahir dari hatinya. Kurasakan pula pelukan Ayah, pelukan dari orang yang menjadi pengganti Ayah kandungku.
Hari ini 28 Februari, hari kelahiranku, dan 22 tahun yang lalu pada tanggal yang sama Catur Aditya–Adit, begitu panggilannya, adik yang sering menjadi bahan cerita Ibu─meninggal setelah Ibu melahirkannya. Saat itu ketika hendak pulang dari membelikan hadiah ulang tahun, seorang pengendara motor ceroboh menyerempet dan menyebabkan Ibu terjatuh sehingga kelahiran yang belum waktunya terjadi. Adit hanya bertahan selama tiga jam.
Kematian Adit sekaligus matinya harapan Ibu untuk memiliki anak kandung. Trauma dan kesedihan yang mendalam serta cidera otak akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Ibu berhalusinasi, berkhayal akan kehadiran Adit. Enam tahun usiaku dan sudah empat tahun aku tinggal bersama mereka saat itu. Iya, empat tahun sebelum peristiwa itu aku telah ditinggal selamanya oleh orang yang seharusnya kupanggil Ayah. Sejak saat itu aku diasuh dan dibesarkan dengan penuh sayang dan cinta oleh mereka yang seharusnya kupanggil Paman dan Bibi dan tiga nisan ini sebagai penanda jasad kedua orang tua kandungku dan Adit, beristirahat abadi di sini. Tiga nisan yang kami kunjungi setiap tanggal 28 Februari.



















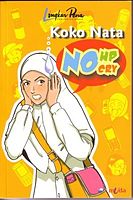
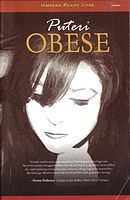
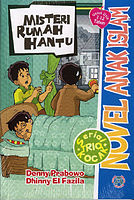


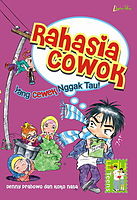


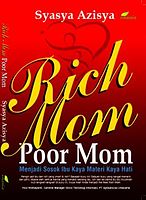



1 komentar:
cerita yang bagus shinta, diambil dari kisah nyata atau referensi buku, aku ingin berdiskusi denganmu lebih lanjut.. terimakasih
23 Februari 2013 pukul 16.24Posting Komentar