Ketika Juru Cerita Meninggalkan Buku
In Angkatan I, In Denny Prabowo, In ESAI, In NonfiksiRabu, 27 Januari 2010
Esai Denny Prabowo
“Ceritkan padaku tentang kehilangan,” kata Upik pada tukang cerita itu. Maka tukang cerita itupun berkisah tentang bandana.
Demikianlah, Seno Gumira Ajidarma (SGA) kerap mengawali ceritanya. Apa yang dilakukan SGA mengingatkan kita pada peran penting seorang juru cerita atau tukang cerita di masa lalu, ketika sastra lisan menjadi satu-satunya media dalam penyampaian ajaran atau pesan. SGA seolah ingin mengembalikan peran itu dalam bentuknya yang lain: tulisan.
Kehadiran seorang juru cerita yang tampil sebagai narator di dalam cerpen-cerpen SGA, membuat pembaca seperti ‘mendengar’, walau pada kenyataannya tetap harus membaca. Ini merupakan bentuk kreativitas yang mungkin sekali mampu mengembalikan kegairahan pada sastra tulis seperti di era Hamzah Fansuri dengan Syair Perahunya yang ditulis pada abad ke-17 M, dan Raja Ali Haji dengan Hikayat Abdul Muluk yang ditulis bersama adiknya—Raja Zaleha pada tahun 1846 M.
Namun, usaha SGA menampilkan ‘suara’ juru cerita di dalam cerpennya, tak cukup membuat kegiatan membaca menjadi lebih mudah daripada mendengar langsung sebuah cerita yang dilisankan. Dan juru cerita pun menemukan eksistensinya dalam bentuk yang lebih mendekati aslinya melalui televisi: iklan, sinetron, telenovela, dan film seri yang mendominasi mata acara TV dapat dijadikan representasi yang pas dari sastra lisan kontemporer ini.
Salah satu keberhasilan sastra lisan dalam menyampaikan pesan dan ajaran adalah karena bentuknya yang audio visual. Cerita yang disampaikan melalui mulut dan peragaan sang juru cerita tentunya lebih mudah diterima. Kita hanya perlu duduk melihat dan mendengar juru cerita menyampaikan sebuah kisah. Berbeda halnya dengan sastra tulis yang membutuhkan energi untuk menekuni tiap kata dalam cerita.
Kehadiran televisi yang menjadi mediator sekaligus narator dalam terbentuknya ‘komunikasi sastra’ yang ditopang simulasi teknologi informasi kian memanjakan kita dalam menerima pesan dan ajaran. TV kemudian menjelma jadi juru cerita yang mendongengkan kisah tanpa harus berjalan door to door, cukup disiarkan melalui pemancar dan juru cerita pun siap menyapa melalui layar kaca di tiap pintu rumah pada waktu yang bersamaan.
Inilah yang sesungguhnya memiliki andil besar terhadap rendahnya minat baca di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik pada 2003 menunjukkan sekitar 84,94 % penduduk usia 10 tahun lebih suka menonton televisi. Hanya 22,06 % saja yang mengatakan suka membaca koran dan majalah. Jadi, jangan heran jika minat baca masyarakat Indonesia di kawasan Asia Tenggara hanya menempati peringkat ke empat di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Agaknya tidak berlebihan kalau dikatakan penetrasi televisi menjadi biang keladi terbesar terkikisnya kebiasaan membaca di masyarakat kita.
Kondisi ini kian diperparah dengan sistem pendidikan yang tak mambuat siswa menjadi akrab dengan buku. Taufik Ismail dalam makalahnya Budaya Membaca dan Menulis yang disampaikan dalam sebuah seminar sastra yang diadakan oleh Forum Studi Islam FEUI, menyampaikan data, pada tahun antara 1939-1942 Algemene Middelbare School (SMA zaman Belanda) Yogyakarta mewajibkan siswa membaca 25 buku sastra dalam waktu tiga tahun, tak jauh di bawah SMA Forest Hill New York yang mewajibkan siswanya membaca 30 buku pada tahun 1987-1989.
Awal tahun 1950, ketika pemerintahan telah sepenuhnya berada di tangan Indonesia, wajib baca 25 buku sastra dan bimbingan menulis digunting habis! Demi mengejar ketertinggalan pembangunan, pemerintah lebih mengunggulkan dan menyanjung jurusan eksakta, ekonomi, dan hukum. Padahal, menurut Taufiq Ismail sastra merupakan stimulus untuk meletakkan dasar kebiasaan dan kesenangan membaca buku, sehingga menjadi jembatan menuju literasi buku apa pun dalam disiplin ilmu yang diambil.
Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa usaha meningkatkan minat baca dari berbagai pihak, maka jangan salahkan jika juru cerita semakin enggan tinggal di dalam buku, dan meninggalakan buku terasing di rak-rak penuh debu. Dengan begitu, penjajahan budaya oleh kaum kapitalis di negeri ini menjadi semakin mudah.
Rumah Cahaya FLP, 29.0807
Sumber: Koran Media Indonesia (nomornya lupa)
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



















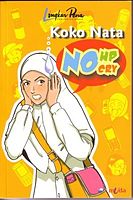
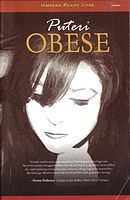
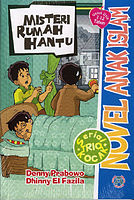


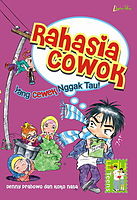


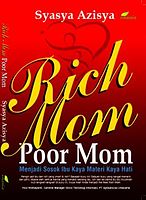



0 komentar:
Posting Komentar