 Cerpen Emil Akbar
Dimuat di Majalah Gong Edisi: 111/X/2009
Seperti tawaf di Ka’bah, saat itu jamaah yang datang dari berbagai daerah, tengah khusyuk mengitari tugu beton yang pernah dibangun Belanda beberapa waktu silam, sambil mengumandangkan kalimat tauhid dengan tubuh bergoyang laksana ilalang yang menari ditiup angin. Ketika gerombolan itu datang menghujat.
“Syirik!”
“Bukan ajaran Islam.”
“Bubarkan!”
***
Aku selalu heran. Ibu sering melarangku pergi ke Malino untuk mengisi liburan semenjak masih SMA sampai sekarang, aku kuliah dan menjadi anak pencinta alam. Paling tidak ibu sering menghalang-halangi niatku dengan berbagai alasan. Padahal di sana aku punya warisan peninggalan ayah, berupa tempat penginapan yang dikelola orang lain. Makanya kerap kali aku berangkat diam-diam. Sepulang dari Malino, ibu pasti tahu dan langsung menghukum dengan cara mendiamkanku beberapa hari. Sejak itu aku tahu ibu tidak pernah ke sana.
Ketika ibu bertanya apa saja yang kulakukan setiap aku berkunjung ke sana, kulihat wajahnya harap-harap cemas seperti was-was yang tak semestinya. Bagai anak kecil yang ketahuan mencuri, kuceritakan semuanya termasuk pengalamanku mendaki puncak gunung Bawakaraeng dan kudapati di sana ada ritual haji. Ibu makin panik dan kian hari mengurung diri di dalam kamar. Saat kutanya kenapa? Ibu bungkam seribu bahasa seperti bertingkah yang tidak kumengerti. Tatkala kini berbaring lemah di rumah sakit, barulah ibu mau bercerita.
“Bunga, kamu punya seorang kakak.”
***
“Kapan kita naik haji, Daeng?” tanya Maniah yang sebenarnya tidak perlu Daeng Tata jawab sebab ia tahu istrinya itu hanya mengeluhkan nasib yang tak pernah bisa simpan uang.
“Sabarlah dulu, Anriku. Bila tiba waktunya, kita pasti akan ke tanah suci. Untuk itu kita jangan putus berdoa,” nasihatnya itu belum mampu meluluhkan hati Maniah yang punya mau.
“Percuma berdoa tanpa usaha, Daeng. Apa yang bisa diandalkan dari sepetak sawah warisan orangtuamu yang tak seberapa itu. Tak cukup bahkan untuk perut kita. Sayuran dan kadang padi yang kita tanam harganya selalu rendah, tidak pernah naik. Kita tinggal di hamparan gunung yang luas tapi milik kita tidak lebih dari secuil. Dan apa pula yang Daeng bisa lakukan selain bertani.”
Daeng Tata meredam amarah yang menghantam dada, berusaha maklum akan ucapan istrinya yang begitu tajam menusuk. Barangkali Maniah tidak sadar tengah menyinggungnya.
Dulu, orangtuanya memang punya banyak tanah. Namun tanah itu dijual murah karena didesak oleh usia mereka untuk naik ke tanah suci sebelum maut menjemput, dan beberapa tanah disita lantaran orangtuanya mengambil pinjaman untuk menambah upah naik haji, sebab uang hasil penjualan tanah belum juga cukup memenuhi ongkos. Juga buat selamatan sebelum dan sesudah naik haji. Harus dilunasi karena sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk membereskan segala hajat yang tertunggak. Beberapa kali Daeng Tata didatangi di dalam mimpi, orangtuanya mengemis memintanya segera membayar utang mereka kepada yang bersangkutan yang memang sering menagih. Padahal sisa tanah yang mereka wariskan adalah biaya hidup Daeng Tata sehari-hari.
Waktu itu, tanah memang seperti tidak ada harganya sebab jarang yang mau beli. Apalagi terletak di daerah puncak. Namun sekarang di tanah itu sudah banyak berdiri Vila, tempat penginapan untuk para pelancong yang berwisata ke Malino yang terkenal dengan air terjun dan udaranya yang sejuk.
“Besok saya akan ke atas, Anri. Kamu mau ikut?” bujuknya agak mengalihkan pembicaraan agar perasaan istrinya sedikit lunak, lantaran malam ini lelaki itu membutuhkannya. Ia memegang bahu istrinya pelan yang sedang berbaring membelakanginya.
“Tidak. Saya tidak percaya lagi, Daeng. Saya capek berangan-angan. Saya tidak mau pahala yang sama dengan naik ke Mekkah di atas gunung Bawakaraeng itu. Apakah Daeng tidak tahu? Banyak yang bilang ibadah ke sana itu keliru.” Maniah menolak secara halus, menggeser pundaknya biar terlepas dari tangan suaminya yang membelai bahunya.
“Ah, tahu apa mereka itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya hendak memaksakan ajaran yang katanya murni!” ujarnya seperti mengumpat. Menghempaskan diri karena merasa gagal melelehkan kebekuan istrinya.
Sungguh Daeng Tata sangat sulit menakhlukkan tabiat istrinya yang keras hati ketika sedang merajuk. Perempuan yang ia nikahi mati-matian sebab ia punya saingan. Ia rela menghabiskan tanah warisannya yang tersisa buat memenuhi permintaan calon mertuanya yang banyak ulah itu, sebab ada orang lain yang juga hendak melamar. Kepada pemberi yang tertinggi, mereka melepas anak gadisnya.
“Daeng, bagaimana kalau saya ke Makassar mencari kerja?” Tiba-tiba Maniah mengajukan usul yang tentu saja mengejutkan Daeng Tata. I strinya membalikkan badan menatapnya. Berkat pelita minyak yang menyala redup, ia bisa melihat mata istrinya yang berbinar, ada semangat di dalamnya.
“Seperti waktu gadis dulu. Saya akan bekerja sebagai buruh pabrik dan bakal menabung,” lanjutnya penuh harap, demikian riang seperti mengejar impian.
“Anri, kau akan lama di sana nantinya. Dengan begitu kau tega meninggalkan saya sendirian di sini.”
“Tidak apa, demi masa depan kita. Kelak bila sudah cukup uang dan pengalaman saya akan mengajakmu serta. Kita buka usaha di sana.”
“Tidak. Saya tidak mengijinkanmu!”
“Daeng, tenang saja. Sesekali saya akan menjengukmu.”
Suaminya bungkam yang bukan hanya diam. Maniah juga sejenak membisu sekedar mencari jawaban yang diinginkannya. Namun air muka Daeng Tata tidak berubah, dan istrinya itu sudah mengerti bahwa ia tidak bakal mendapatkan restu untuk pergi. Sambil kembali membalikkan badan, ia tetap menceracau. Tak mau menyerah.
“Kakak-kakakku sudah haji semua. Adik lelakiku yang pedagang itu sudah berangkat. Saya saja yang melarat seperti ini,” suaranya lirih menyindir. Namun ia tidak memperoleh tanggapan selain sunyi.
“Besok, naiklah ke atas supaya diberi gelar Haji Bawakaraeng. Teruslah seperti itu, sampai kapan pun, Daeng tidak akan mampu naik haji.”
Maniah diambang putus asa, memadamkan lampu minyak. Tidak peduli lagi dengan suaminya yang malam itu berhasrat bikin anak. Boleh jadi istrinya itu sering uring-uringan lantaran belum melahirkan buah hati. Pernah Daeng Tata dan maniah mendatangi sanro untuk berobat setelah lama menunggu. Namun dukun itu menyurutkan harapan. Katanya, Daeng Tata punya mani yang terlalu panas hingga mematikan indung telur. Lain hari berujar, rahim Maniah telah dingin dan beku. Terakhir menyimpulkan, mereka tidak cocok.
Daeng Tata tidak bisa tidur, memandang nanar gelap yang mengerubungi.
***
Dan Sekarang aku berada di sini untuk menemuinya.
Di atas gunung Bawakaraeng, angin menampar tubuh ringkih Daeng Tata yang tak goyah, memandang jauh di bawah sana. Bagai di laut, langit merendah begitu dekat sebab puncak bukit itu menjulang seperti hendak menjangkau cakrawala dengan gumpalan mega-mega berarak-arak serupa ombak yang tak surut, bergulung-gulung dengan pekatnya. Tampak megah keemasan pada senja yang bangkit, pertanda malam akan memeluk hari. Dan setiap kali awan itu melintas, bayangannya tampak berkejaran di permukaan bumi.
Deru angin terus menerpanerpa. Hembusan itu bertiup kencang membuat celana kain dan baju lusuh serta sarung yang tersampir di pundaknya berkibar-kibar ke belakang. Kopiah hitam bertengger di kepalanya yang beruban pun telah pudar serupa dirinya yang digerogoti usia.
Lelaki tua itu masih menatap, barangkali nun pada hamparan kota Makassar yang merajalela, tanah daratan yang jauh dari sini dan hidup dengan gemerlap, kelap-kelip yang mengalahkan kedap-kedip bintang yang mulai bermunculan di langit yang sebentar lagi menghitam, seperti perempuan nakal yang main mata.
Aku sejak tadi mengamatinya dari jarak yang tak dekat. Agak ke bawah, di balik hutan yang dihuni halimun, kabut asap tipis nan dingin yang lalu lalang. Aku melangkah mendekatinya dengan kaki kuseret biar berisik supaya ia berpaling, tapi Daeng Tata tetap bergeming hingga aku berada sejajar dengannya. Dingin kian merasuk mungkin sampai tulang, ngilu yang membeku. Aku menggigil seperti digigit oleh dingin, membuat gigiku ingin bergemelutuk dan akan mengeluarkan uap es ketika aku berbicara dan bibirku kini menjadi kelu. Padahal badanku dibungkus jaket tebal bagai berbalut-balut. Aku seperti hendak meringkus diri pada kedua tanganku yang bersilang di atas dada.
Berbeda sekali dengan Daeng Tata yang santai saja menautkan kedua tangannya di belakang punggung karena sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Aku yakin telapak tangannya akan berkeringat dan kulitnya bakal meleleh lantaran peluh, tatkala nanti ia ke Makassar yang teriknya garang dengan niat mencari anaknya yang tak pernah menjenguknya beberapa tahun ini, semenjak pertengkaran yang aku pun tahu. Bagai menunaikan hajat ke tanah suci yang tak pernah terwujud karena uangnya tidak pernah cukup dan tiap tahun biayanya selalu naik.
Sungguh lelaki tua di sampingku ini seakan tidak bisa berpisah dari gunung Bawakaraeng yang ia jaga melebihi dari hidupnya. Ia menanam Mahoni dan jati serta pohon jenis lainnya di lereng bukit, dan di lokasi yang pohonnya terbabat di sekitar gunung. Bibitnya ia semai di pekarangan rumahnya. Sebab jasanya itu ia mendapatkan upah tiap bulan dari pemerintah Gowa yang tidak cukup buat makan berhari-hari. Lembaran uang itu ia tabung dalam kaleng biscuit entah berapa tahun, yang telah penuh. Namun jika dikumpulkan dan diikat dengan karet jumlahnya tak seberapa, tidak sebanding dengan jerih payahnya. Aku mengetahuinya sebab ia bermaksud menitipkan segepok uang itu beberapa hari yang lalu kepadaku buat Amiruddin, anaknya. Uang kuliah untuk temanku itu. Dulu memang anaknya adalah temanku tapi setelah aku tahu semuanya, dia bukan lagi temanku. Lebih dari itu. Aku bilang, Amiruddin memiliki usaha yang tidak tetap.
“Bunga, sampaikan salam saya pada Anakku yang masih keras hati. Bilang, saya sangat merindukannya,” ujarnya lembut nan tegas tanpa melepas pandang melihat kota Makassar yang berkilau gemilang serupa lampu senter yang benderang di tengah kegelapan, seperti kumpulan cahaya.
“Tata, tahu sendiri sikapnya yang tak mau dengar. Dan aku tidak bisa memaksa,” kataku setelah agak lama terdiam, lantaran aku sibuk menghalau dingin yang kian merayap pada hawa yang mulai senyap. Kulihat pelita di rumah penduduk di kaki dan di pinggang gunung sudah mulai berkeliaran bagai percikan sinar yang menyebar, bak kunang-kunang yang saling menjauh mencari tempat hinggap.
“Bujuk dia sampai mau. Katakan lagi padanya bahwa saya akan minta maaf, kalau perlu saya akan bersujud di kakinya. Akan kutinggalkan semua kebiasaan yang dimatanya adalah dosa. Hanya dia satu-satunya harapanku, Bunga. Harta warisan peninggalan almarhumah istriku yang ingin kususul di tanah suci. Dialah yang dapat mewujudkannya.” Kali ini ia menjenguk mukaku yang hampir beku, menatap asa begitu memelas.
“Iye, Tata, akan aku usahakan,” ucapku dengan gigi bergeretak. Kendati aku tidak tahu dimana Amiruddin sekarang. Namun aku yakin tidak susah untuk menemukannya. Sebab dia tidak kuliah lagi. Lebih memilih menyeru jalan agama ketimbang menuntut ilmu di fakultas yang katanya tidak dibawa ke akhirat.
***
“Aku belum menikah karena belum bisa melupakanmu. Dan aku akan terus menunggu sampai kamu mau, Maniah.” Sungai Jene Berang mengalir deras seperti meluap, menenggelamkan bongkahan batu kali yang terserak. Maniah bagai terseret oleh arusnya, telinganya berdengung mendengar ucapan Andi Baso. Pertemuan di tepi sungai di suatu pagi yang hendak beranjak, ketika Maniah usai membasuh diri dan membersihkan cucian.
“Saya sudah punya Daeng Tata!” jawab Maniah bergetar, agak terperangah. Meraba-raba kemauan hatinya.
“Itu bukan masalah jika kamu mau.”
Maniah menatap lelaki itu begitu lama seperti hendak menemukan keseriusan. Lelaki yang pernah ditolak sebab tak mampu memenuhi permintaan orangtuanya, sehingga Maniah mengubur cintanya dalam-dalam. Pertemuan itu rutin meski tidak setiap pagi dan kadang di tempat berbeda yang tidak diketahui orang lain, saat sepi. Sampai kesalahan itu diperbuat, yang membuat Daeng Tata senang karena tidak tahu.
“Kamu hamil, Maniah?”
Perempuan itu tidak mampu berterus terang karena didera dosa. Ia gelap mata. Andi Baso sangat sulit diabaikan. Bukan hanya karena ada hati, melainkan menjanjikan hidup layak dan nantinya bisa naik haji. Lelaki itu telah mapan. Kupingnya sudah terlalu panas mendengar segala gunjingan hina akan hidupnya yang tak kunjung membaik.
Maniah merasa tidak dipandang di tengah keluarga dan di setiap pesta yang dikunjunginya. Tidak diperbolehkan berjejer menyambut tamu di ruang depan karena belum haji. Cuma kerap mendapat tempat di dapur dan dianggap serupa asap yang mengepul lalu lenyap tak bersisa dan tak ada yang peduli. Hanya disuruh bantu-bantu memasak. Lantaran malu, ia tak tahan. Ketika kesempatan itu memberi peluang tak mungkin ia tampik kendati meninggalkan aib.
“Bayi itu anakku, Maniah.”
“Tidak Andi Baso. Daeng Tata sangat mengharapkannya. Saya akan menyusulmu nanti setelah saya melahirkan.”
***
Daeng Tata masih menatapku begitu teduh penuh pancaran kasih seperti menganggap aku adalah anaknya.
“Terima kasih, Bunga. Mari kita turun. Sepertinya kamu sudah tidak tahan dingin. Teman-temanmu juga sudah lama memanggil. Kamu tahu, Bunga? Kamu mirip istriku waktu muda.”
Aku tidak tersipu dengan gurauannya. Aku malah makin merasa bersalah. Ah, seandainya Daeng Tata tahu tentang rahasia yang kubawa, titipan pesan dari ibu yang mesti kusampaikan. Mengenai masa lalu yang tak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengatakan, istrimu belum mati dan Amiruddin bukan anakmu. Namun mulutku ini tak sampai hati mengutarakan maksud di setiap kesempatan berdua dengannya seperti tercekat di tenggerokan. Padahal besok aku sudah kembali ke Makassar.
Teman-temanku sudah membereskan segala peralatan camping tak terkecuali sisa-sisa berupa sampah. Memastikan tak ada yang ketinggalan, semuanya ada dalam ransel besar di pundak. Setelah berucap syukur, kami siap turun gunung. Di lembah Ramma, di rumah panggung Daeng Tata, kami akan istirahat. Barangkali sampai pagi meninggalkan hari. Semoga kesempatan terakhir itu tidak aku siasiakan untuk membuka mulut, atau tidak sama sekali.
***
Sinjai, 29 Oktober 2008
Catatan:
Gunung Bawakaraeng yang berarti Mulut Tuhan adalah tempat Syekh Yusuf berangkat ke Mekkah. Ulama sufi yang paling terkenal di seantero Sulawesi, dipercaya masyarakat bagai ditelan lalu hilang dan muncul di tanah suci. Dari sini awal mula ritual haji Bawakaraeng.
Daeng: Panggilan sayang untuk suami yang berarti kakak.
Anri: panggilan sayang untuk istri yang berarti adik.
Cerpen Emil Akbar
Dimuat di Majalah Gong Edisi: 111/X/2009
Seperti tawaf di Ka’bah, saat itu jamaah yang datang dari berbagai daerah, tengah khusyuk mengitari tugu beton yang pernah dibangun Belanda beberapa waktu silam, sambil mengumandangkan kalimat tauhid dengan tubuh bergoyang laksana ilalang yang menari ditiup angin. Ketika gerombolan itu datang menghujat.
“Syirik!”
“Bukan ajaran Islam.”
“Bubarkan!”
***
Aku selalu heran. Ibu sering melarangku pergi ke Malino untuk mengisi liburan semenjak masih SMA sampai sekarang, aku kuliah dan menjadi anak pencinta alam. Paling tidak ibu sering menghalang-halangi niatku dengan berbagai alasan. Padahal di sana aku punya warisan peninggalan ayah, berupa tempat penginapan yang dikelola orang lain. Makanya kerap kali aku berangkat diam-diam. Sepulang dari Malino, ibu pasti tahu dan langsung menghukum dengan cara mendiamkanku beberapa hari. Sejak itu aku tahu ibu tidak pernah ke sana.
Ketika ibu bertanya apa saja yang kulakukan setiap aku berkunjung ke sana, kulihat wajahnya harap-harap cemas seperti was-was yang tak semestinya. Bagai anak kecil yang ketahuan mencuri, kuceritakan semuanya termasuk pengalamanku mendaki puncak gunung Bawakaraeng dan kudapati di sana ada ritual haji. Ibu makin panik dan kian hari mengurung diri di dalam kamar. Saat kutanya kenapa? Ibu bungkam seribu bahasa seperti bertingkah yang tidak kumengerti. Tatkala kini berbaring lemah di rumah sakit, barulah ibu mau bercerita.
“Bunga, kamu punya seorang kakak.”
***
“Kapan kita naik haji, Daeng?” tanya Maniah yang sebenarnya tidak perlu Daeng Tata jawab sebab ia tahu istrinya itu hanya mengeluhkan nasib yang tak pernah bisa simpan uang.
“Sabarlah dulu, Anriku. Bila tiba waktunya, kita pasti akan ke tanah suci. Untuk itu kita jangan putus berdoa,” nasihatnya itu belum mampu meluluhkan hati Maniah yang punya mau.
“Percuma berdoa tanpa usaha, Daeng. Apa yang bisa diandalkan dari sepetak sawah warisan orangtuamu yang tak seberapa itu. Tak cukup bahkan untuk perut kita. Sayuran dan kadang padi yang kita tanam harganya selalu rendah, tidak pernah naik. Kita tinggal di hamparan gunung yang luas tapi milik kita tidak lebih dari secuil. Dan apa pula yang Daeng bisa lakukan selain bertani.”
Daeng Tata meredam amarah yang menghantam dada, berusaha maklum akan ucapan istrinya yang begitu tajam menusuk. Barangkali Maniah tidak sadar tengah menyinggungnya.
Dulu, orangtuanya memang punya banyak tanah. Namun tanah itu dijual murah karena didesak oleh usia mereka untuk naik ke tanah suci sebelum maut menjemput, dan beberapa tanah disita lantaran orangtuanya mengambil pinjaman untuk menambah upah naik haji, sebab uang hasil penjualan tanah belum juga cukup memenuhi ongkos. Juga buat selamatan sebelum dan sesudah naik haji. Harus dilunasi karena sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk membereskan segala hajat yang tertunggak. Beberapa kali Daeng Tata didatangi di dalam mimpi, orangtuanya mengemis memintanya segera membayar utang mereka kepada yang bersangkutan yang memang sering menagih. Padahal sisa tanah yang mereka wariskan adalah biaya hidup Daeng Tata sehari-hari.
Waktu itu, tanah memang seperti tidak ada harganya sebab jarang yang mau beli. Apalagi terletak di daerah puncak. Namun sekarang di tanah itu sudah banyak berdiri Vila, tempat penginapan untuk para pelancong yang berwisata ke Malino yang terkenal dengan air terjun dan udaranya yang sejuk.
“Besok saya akan ke atas, Anri. Kamu mau ikut?” bujuknya agak mengalihkan pembicaraan agar perasaan istrinya sedikit lunak, lantaran malam ini lelaki itu membutuhkannya. Ia memegang bahu istrinya pelan yang sedang berbaring membelakanginya.
“Tidak. Saya tidak percaya lagi, Daeng. Saya capek berangan-angan. Saya tidak mau pahala yang sama dengan naik ke Mekkah di atas gunung Bawakaraeng itu. Apakah Daeng tidak tahu? Banyak yang bilang ibadah ke sana itu keliru.” Maniah menolak secara halus, menggeser pundaknya biar terlepas dari tangan suaminya yang membelai bahunya.
“Ah, tahu apa mereka itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya hendak memaksakan ajaran yang katanya murni!” ujarnya seperti mengumpat. Menghempaskan diri karena merasa gagal melelehkan kebekuan istrinya.
Sungguh Daeng Tata sangat sulit menakhlukkan tabiat istrinya yang keras hati ketika sedang merajuk. Perempuan yang ia nikahi mati-matian sebab ia punya saingan. Ia rela menghabiskan tanah warisannya yang tersisa buat memenuhi permintaan calon mertuanya yang banyak ulah itu, sebab ada orang lain yang juga hendak melamar. Kepada pemberi yang tertinggi, mereka melepas anak gadisnya.
“Daeng, bagaimana kalau saya ke Makassar mencari kerja?” Tiba-tiba Maniah mengajukan usul yang tentu saja mengejutkan Daeng Tata. I strinya membalikkan badan menatapnya. Berkat pelita minyak yang menyala redup, ia bisa melihat mata istrinya yang berbinar, ada semangat di dalamnya.
“Seperti waktu gadis dulu. Saya akan bekerja sebagai buruh pabrik dan bakal menabung,” lanjutnya penuh harap, demikian riang seperti mengejar impian.
“Anri, kau akan lama di sana nantinya. Dengan begitu kau tega meninggalkan saya sendirian di sini.”
“Tidak apa, demi masa depan kita. Kelak bila sudah cukup uang dan pengalaman saya akan mengajakmu serta. Kita buka usaha di sana.”
“Tidak. Saya tidak mengijinkanmu!”
“Daeng, tenang saja. Sesekali saya akan menjengukmu.”
Suaminya bungkam yang bukan hanya diam. Maniah juga sejenak membisu sekedar mencari jawaban yang diinginkannya. Namun air muka Daeng Tata tidak berubah, dan istrinya itu sudah mengerti bahwa ia tidak bakal mendapatkan restu untuk pergi. Sambil kembali membalikkan badan, ia tetap menceracau. Tak mau menyerah.
“Kakak-kakakku sudah haji semua. Adik lelakiku yang pedagang itu sudah berangkat. Saya saja yang melarat seperti ini,” suaranya lirih menyindir. Namun ia tidak memperoleh tanggapan selain sunyi.
“Besok, naiklah ke atas supaya diberi gelar Haji Bawakaraeng. Teruslah seperti itu, sampai kapan pun, Daeng tidak akan mampu naik haji.”
Maniah diambang putus asa, memadamkan lampu minyak. Tidak peduli lagi dengan suaminya yang malam itu berhasrat bikin anak. Boleh jadi istrinya itu sering uring-uringan lantaran belum melahirkan buah hati. Pernah Daeng Tata dan maniah mendatangi sanro untuk berobat setelah lama menunggu. Namun dukun itu menyurutkan harapan. Katanya, Daeng Tata punya mani yang terlalu panas hingga mematikan indung telur. Lain hari berujar, rahim Maniah telah dingin dan beku. Terakhir menyimpulkan, mereka tidak cocok.
Daeng Tata tidak bisa tidur, memandang nanar gelap yang mengerubungi.
***
Dan Sekarang aku berada di sini untuk menemuinya.
Di atas gunung Bawakaraeng, angin menampar tubuh ringkih Daeng Tata yang tak goyah, memandang jauh di bawah sana. Bagai di laut, langit merendah begitu dekat sebab puncak bukit itu menjulang seperti hendak menjangkau cakrawala dengan gumpalan mega-mega berarak-arak serupa ombak yang tak surut, bergulung-gulung dengan pekatnya. Tampak megah keemasan pada senja yang bangkit, pertanda malam akan memeluk hari. Dan setiap kali awan itu melintas, bayangannya tampak berkejaran di permukaan bumi.
Deru angin terus menerpanerpa. Hembusan itu bertiup kencang membuat celana kain dan baju lusuh serta sarung yang tersampir di pundaknya berkibar-kibar ke belakang. Kopiah hitam bertengger di kepalanya yang beruban pun telah pudar serupa dirinya yang digerogoti usia.
Lelaki tua itu masih menatap, barangkali nun pada hamparan kota Makassar yang merajalela, tanah daratan yang jauh dari sini dan hidup dengan gemerlap, kelap-kelip yang mengalahkan kedap-kedip bintang yang mulai bermunculan di langit yang sebentar lagi menghitam, seperti perempuan nakal yang main mata.
Aku sejak tadi mengamatinya dari jarak yang tak dekat. Agak ke bawah, di balik hutan yang dihuni halimun, kabut asap tipis nan dingin yang lalu lalang. Aku melangkah mendekatinya dengan kaki kuseret biar berisik supaya ia berpaling, tapi Daeng Tata tetap bergeming hingga aku berada sejajar dengannya. Dingin kian merasuk mungkin sampai tulang, ngilu yang membeku. Aku menggigil seperti digigit oleh dingin, membuat gigiku ingin bergemelutuk dan akan mengeluarkan uap es ketika aku berbicara dan bibirku kini menjadi kelu. Padahal badanku dibungkus jaket tebal bagai berbalut-balut. Aku seperti hendak meringkus diri pada kedua tanganku yang bersilang di atas dada.
Berbeda sekali dengan Daeng Tata yang santai saja menautkan kedua tangannya di belakang punggung karena sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Aku yakin telapak tangannya akan berkeringat dan kulitnya bakal meleleh lantaran peluh, tatkala nanti ia ke Makassar yang teriknya garang dengan niat mencari anaknya yang tak pernah menjenguknya beberapa tahun ini, semenjak pertengkaran yang aku pun tahu. Bagai menunaikan hajat ke tanah suci yang tak pernah terwujud karena uangnya tidak pernah cukup dan tiap tahun biayanya selalu naik.
Sungguh lelaki tua di sampingku ini seakan tidak bisa berpisah dari gunung Bawakaraeng yang ia jaga melebihi dari hidupnya. Ia menanam Mahoni dan jati serta pohon jenis lainnya di lereng bukit, dan di lokasi yang pohonnya terbabat di sekitar gunung. Bibitnya ia semai di pekarangan rumahnya. Sebab jasanya itu ia mendapatkan upah tiap bulan dari pemerintah Gowa yang tidak cukup buat makan berhari-hari. Lembaran uang itu ia tabung dalam kaleng biscuit entah berapa tahun, yang telah penuh. Namun jika dikumpulkan dan diikat dengan karet jumlahnya tak seberapa, tidak sebanding dengan jerih payahnya. Aku mengetahuinya sebab ia bermaksud menitipkan segepok uang itu beberapa hari yang lalu kepadaku buat Amiruddin, anaknya. Uang kuliah untuk temanku itu. Dulu memang anaknya adalah temanku tapi setelah aku tahu semuanya, dia bukan lagi temanku. Lebih dari itu. Aku bilang, Amiruddin memiliki usaha yang tidak tetap.
“Bunga, sampaikan salam saya pada Anakku yang masih keras hati. Bilang, saya sangat merindukannya,” ujarnya lembut nan tegas tanpa melepas pandang melihat kota Makassar yang berkilau gemilang serupa lampu senter yang benderang di tengah kegelapan, seperti kumpulan cahaya.
“Tata, tahu sendiri sikapnya yang tak mau dengar. Dan aku tidak bisa memaksa,” kataku setelah agak lama terdiam, lantaran aku sibuk menghalau dingin yang kian merayap pada hawa yang mulai senyap. Kulihat pelita di rumah penduduk di kaki dan di pinggang gunung sudah mulai berkeliaran bagai percikan sinar yang menyebar, bak kunang-kunang yang saling menjauh mencari tempat hinggap.
“Bujuk dia sampai mau. Katakan lagi padanya bahwa saya akan minta maaf, kalau perlu saya akan bersujud di kakinya. Akan kutinggalkan semua kebiasaan yang dimatanya adalah dosa. Hanya dia satu-satunya harapanku, Bunga. Harta warisan peninggalan almarhumah istriku yang ingin kususul di tanah suci. Dialah yang dapat mewujudkannya.” Kali ini ia menjenguk mukaku yang hampir beku, menatap asa begitu memelas.
“Iye, Tata, akan aku usahakan,” ucapku dengan gigi bergeretak. Kendati aku tidak tahu dimana Amiruddin sekarang. Namun aku yakin tidak susah untuk menemukannya. Sebab dia tidak kuliah lagi. Lebih memilih menyeru jalan agama ketimbang menuntut ilmu di fakultas yang katanya tidak dibawa ke akhirat.
***
“Aku belum menikah karena belum bisa melupakanmu. Dan aku akan terus menunggu sampai kamu mau, Maniah.” Sungai Jene Berang mengalir deras seperti meluap, menenggelamkan bongkahan batu kali yang terserak. Maniah bagai terseret oleh arusnya, telinganya berdengung mendengar ucapan Andi Baso. Pertemuan di tepi sungai di suatu pagi yang hendak beranjak, ketika Maniah usai membasuh diri dan membersihkan cucian.
“Saya sudah punya Daeng Tata!” jawab Maniah bergetar, agak terperangah. Meraba-raba kemauan hatinya.
“Itu bukan masalah jika kamu mau.”
Maniah menatap lelaki itu begitu lama seperti hendak menemukan keseriusan. Lelaki yang pernah ditolak sebab tak mampu memenuhi permintaan orangtuanya, sehingga Maniah mengubur cintanya dalam-dalam. Pertemuan itu rutin meski tidak setiap pagi dan kadang di tempat berbeda yang tidak diketahui orang lain, saat sepi. Sampai kesalahan itu diperbuat, yang membuat Daeng Tata senang karena tidak tahu.
“Kamu hamil, Maniah?”
Perempuan itu tidak mampu berterus terang karena didera dosa. Ia gelap mata. Andi Baso sangat sulit diabaikan. Bukan hanya karena ada hati, melainkan menjanjikan hidup layak dan nantinya bisa naik haji. Lelaki itu telah mapan. Kupingnya sudah terlalu panas mendengar segala gunjingan hina akan hidupnya yang tak kunjung membaik.
Maniah merasa tidak dipandang di tengah keluarga dan di setiap pesta yang dikunjunginya. Tidak diperbolehkan berjejer menyambut tamu di ruang depan karena belum haji. Cuma kerap mendapat tempat di dapur dan dianggap serupa asap yang mengepul lalu lenyap tak bersisa dan tak ada yang peduli. Hanya disuruh bantu-bantu memasak. Lantaran malu, ia tak tahan. Ketika kesempatan itu memberi peluang tak mungkin ia tampik kendati meninggalkan aib.
“Bayi itu anakku, Maniah.”
“Tidak Andi Baso. Daeng Tata sangat mengharapkannya. Saya akan menyusulmu nanti setelah saya melahirkan.”
***
Daeng Tata masih menatapku begitu teduh penuh pancaran kasih seperti menganggap aku adalah anaknya.
“Terima kasih, Bunga. Mari kita turun. Sepertinya kamu sudah tidak tahan dingin. Teman-temanmu juga sudah lama memanggil. Kamu tahu, Bunga? Kamu mirip istriku waktu muda.”
Aku tidak tersipu dengan gurauannya. Aku malah makin merasa bersalah. Ah, seandainya Daeng Tata tahu tentang rahasia yang kubawa, titipan pesan dari ibu yang mesti kusampaikan. Mengenai masa lalu yang tak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengatakan, istrimu belum mati dan Amiruddin bukan anakmu. Namun mulutku ini tak sampai hati mengutarakan maksud di setiap kesempatan berdua dengannya seperti tercekat di tenggerokan. Padahal besok aku sudah kembali ke Makassar.
Teman-temanku sudah membereskan segala peralatan camping tak terkecuali sisa-sisa berupa sampah. Memastikan tak ada yang ketinggalan, semuanya ada dalam ransel besar di pundak. Setelah berucap syukur, kami siap turun gunung. Di lembah Ramma, di rumah panggung Daeng Tata, kami akan istirahat. Barangkali sampai pagi meninggalkan hari. Semoga kesempatan terakhir itu tidak aku siasiakan untuk membuka mulut, atau tidak sama sekali.
***
Sinjai, 29 Oktober 2008
Catatan:
Gunung Bawakaraeng yang berarti Mulut Tuhan adalah tempat Syekh Yusuf berangkat ke Mekkah. Ulama sufi yang paling terkenal di seantero Sulawesi, dipercaya masyarakat bagai ditelan lalu hilang dan muncul di tanah suci. Dari sini awal mula ritual haji Bawakaraeng.
Daeng: Panggilan sayang untuk suami yang berarti kakak.
Anri: panggilan sayang untuk istri yang berarti adik.
Haji Bawakaraeng
In CERPEN, In Emil Akbar, In Fiksi DewasaSenin, 16 Maret 2009
 Cerpen Emil Akbar
Dimuat di Majalah Gong Edisi: 111/X/2009
Seperti tawaf di Ka’bah, saat itu jamaah yang datang dari berbagai daerah, tengah khusyuk mengitari tugu beton yang pernah dibangun Belanda beberapa waktu silam, sambil mengumandangkan kalimat tauhid dengan tubuh bergoyang laksana ilalang yang menari ditiup angin. Ketika gerombolan itu datang menghujat.
“Syirik!”
“Bukan ajaran Islam.”
“Bubarkan!”
***
Aku selalu heran. Ibu sering melarangku pergi ke Malino untuk mengisi liburan semenjak masih SMA sampai sekarang, aku kuliah dan menjadi anak pencinta alam. Paling tidak ibu sering menghalang-halangi niatku dengan berbagai alasan. Padahal di sana aku punya warisan peninggalan ayah, berupa tempat penginapan yang dikelola orang lain. Makanya kerap kali aku berangkat diam-diam. Sepulang dari Malino, ibu pasti tahu dan langsung menghukum dengan cara mendiamkanku beberapa hari. Sejak itu aku tahu ibu tidak pernah ke sana.
Ketika ibu bertanya apa saja yang kulakukan setiap aku berkunjung ke sana, kulihat wajahnya harap-harap cemas seperti was-was yang tak semestinya. Bagai anak kecil yang ketahuan mencuri, kuceritakan semuanya termasuk pengalamanku mendaki puncak gunung Bawakaraeng dan kudapati di sana ada ritual haji. Ibu makin panik dan kian hari mengurung diri di dalam kamar. Saat kutanya kenapa? Ibu bungkam seribu bahasa seperti bertingkah yang tidak kumengerti. Tatkala kini berbaring lemah di rumah sakit, barulah ibu mau bercerita.
“Bunga, kamu punya seorang kakak.”
***
“Kapan kita naik haji, Daeng?” tanya Maniah yang sebenarnya tidak perlu Daeng Tata jawab sebab ia tahu istrinya itu hanya mengeluhkan nasib yang tak pernah bisa simpan uang.
“Sabarlah dulu, Anriku. Bila tiba waktunya, kita pasti akan ke tanah suci. Untuk itu kita jangan putus berdoa,” nasihatnya itu belum mampu meluluhkan hati Maniah yang punya mau.
“Percuma berdoa tanpa usaha, Daeng. Apa yang bisa diandalkan dari sepetak sawah warisan orangtuamu yang tak seberapa itu. Tak cukup bahkan untuk perut kita. Sayuran dan kadang padi yang kita tanam harganya selalu rendah, tidak pernah naik. Kita tinggal di hamparan gunung yang luas tapi milik kita tidak lebih dari secuil. Dan apa pula yang Daeng bisa lakukan selain bertani.”
Daeng Tata meredam amarah yang menghantam dada, berusaha maklum akan ucapan istrinya yang begitu tajam menusuk. Barangkali Maniah tidak sadar tengah menyinggungnya.
Dulu, orangtuanya memang punya banyak tanah. Namun tanah itu dijual murah karena didesak oleh usia mereka untuk naik ke tanah suci sebelum maut menjemput, dan beberapa tanah disita lantaran orangtuanya mengambil pinjaman untuk menambah upah naik haji, sebab uang hasil penjualan tanah belum juga cukup memenuhi ongkos. Juga buat selamatan sebelum dan sesudah naik haji. Harus dilunasi karena sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk membereskan segala hajat yang tertunggak. Beberapa kali Daeng Tata didatangi di dalam mimpi, orangtuanya mengemis memintanya segera membayar utang mereka kepada yang bersangkutan yang memang sering menagih. Padahal sisa tanah yang mereka wariskan adalah biaya hidup Daeng Tata sehari-hari.
Waktu itu, tanah memang seperti tidak ada harganya sebab jarang yang mau beli. Apalagi terletak di daerah puncak. Namun sekarang di tanah itu sudah banyak berdiri Vila, tempat penginapan untuk para pelancong yang berwisata ke Malino yang terkenal dengan air terjun dan udaranya yang sejuk.
“Besok saya akan ke atas, Anri. Kamu mau ikut?” bujuknya agak mengalihkan pembicaraan agar perasaan istrinya sedikit lunak, lantaran malam ini lelaki itu membutuhkannya. Ia memegang bahu istrinya pelan yang sedang berbaring membelakanginya.
“Tidak. Saya tidak percaya lagi, Daeng. Saya capek berangan-angan. Saya tidak mau pahala yang sama dengan naik ke Mekkah di atas gunung Bawakaraeng itu. Apakah Daeng tidak tahu? Banyak yang bilang ibadah ke sana itu keliru.” Maniah menolak secara halus, menggeser pundaknya biar terlepas dari tangan suaminya yang membelai bahunya.
“Ah, tahu apa mereka itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya hendak memaksakan ajaran yang katanya murni!” ujarnya seperti mengumpat. Menghempaskan diri karena merasa gagal melelehkan kebekuan istrinya.
Sungguh Daeng Tata sangat sulit menakhlukkan tabiat istrinya yang keras hati ketika sedang merajuk. Perempuan yang ia nikahi mati-matian sebab ia punya saingan. Ia rela menghabiskan tanah warisannya yang tersisa buat memenuhi permintaan calon mertuanya yang banyak ulah itu, sebab ada orang lain yang juga hendak melamar. Kepada pemberi yang tertinggi, mereka melepas anak gadisnya.
“Daeng, bagaimana kalau saya ke Makassar mencari kerja?” Tiba-tiba Maniah mengajukan usul yang tentu saja mengejutkan Daeng Tata. I strinya membalikkan badan menatapnya. Berkat pelita minyak yang menyala redup, ia bisa melihat mata istrinya yang berbinar, ada semangat di dalamnya.
“Seperti waktu gadis dulu. Saya akan bekerja sebagai buruh pabrik dan bakal menabung,” lanjutnya penuh harap, demikian riang seperti mengejar impian.
“Anri, kau akan lama di sana nantinya. Dengan begitu kau tega meninggalkan saya sendirian di sini.”
“Tidak apa, demi masa depan kita. Kelak bila sudah cukup uang dan pengalaman saya akan mengajakmu serta. Kita buka usaha di sana.”
“Tidak. Saya tidak mengijinkanmu!”
“Daeng, tenang saja. Sesekali saya akan menjengukmu.”
Suaminya bungkam yang bukan hanya diam. Maniah juga sejenak membisu sekedar mencari jawaban yang diinginkannya. Namun air muka Daeng Tata tidak berubah, dan istrinya itu sudah mengerti bahwa ia tidak bakal mendapatkan restu untuk pergi. Sambil kembali membalikkan badan, ia tetap menceracau. Tak mau menyerah.
“Kakak-kakakku sudah haji semua. Adik lelakiku yang pedagang itu sudah berangkat. Saya saja yang melarat seperti ini,” suaranya lirih menyindir. Namun ia tidak memperoleh tanggapan selain sunyi.
“Besok, naiklah ke atas supaya diberi gelar Haji Bawakaraeng. Teruslah seperti itu, sampai kapan pun, Daeng tidak akan mampu naik haji.”
Maniah diambang putus asa, memadamkan lampu minyak. Tidak peduli lagi dengan suaminya yang malam itu berhasrat bikin anak. Boleh jadi istrinya itu sering uring-uringan lantaran belum melahirkan buah hati. Pernah Daeng Tata dan maniah mendatangi sanro untuk berobat setelah lama menunggu. Namun dukun itu menyurutkan harapan. Katanya, Daeng Tata punya mani yang terlalu panas hingga mematikan indung telur. Lain hari berujar, rahim Maniah telah dingin dan beku. Terakhir menyimpulkan, mereka tidak cocok.
Daeng Tata tidak bisa tidur, memandang nanar gelap yang mengerubungi.
***
Dan Sekarang aku berada di sini untuk menemuinya.
Di atas gunung Bawakaraeng, angin menampar tubuh ringkih Daeng Tata yang tak goyah, memandang jauh di bawah sana. Bagai di laut, langit merendah begitu dekat sebab puncak bukit itu menjulang seperti hendak menjangkau cakrawala dengan gumpalan mega-mega berarak-arak serupa ombak yang tak surut, bergulung-gulung dengan pekatnya. Tampak megah keemasan pada senja yang bangkit, pertanda malam akan memeluk hari. Dan setiap kali awan itu melintas, bayangannya tampak berkejaran di permukaan bumi.
Deru angin terus menerpanerpa. Hembusan itu bertiup kencang membuat celana kain dan baju lusuh serta sarung yang tersampir di pundaknya berkibar-kibar ke belakang. Kopiah hitam bertengger di kepalanya yang beruban pun telah pudar serupa dirinya yang digerogoti usia.
Lelaki tua itu masih menatap, barangkali nun pada hamparan kota Makassar yang merajalela, tanah daratan yang jauh dari sini dan hidup dengan gemerlap, kelap-kelip yang mengalahkan kedap-kedip bintang yang mulai bermunculan di langit yang sebentar lagi menghitam, seperti perempuan nakal yang main mata.
Aku sejak tadi mengamatinya dari jarak yang tak dekat. Agak ke bawah, di balik hutan yang dihuni halimun, kabut asap tipis nan dingin yang lalu lalang. Aku melangkah mendekatinya dengan kaki kuseret biar berisik supaya ia berpaling, tapi Daeng Tata tetap bergeming hingga aku berada sejajar dengannya. Dingin kian merasuk mungkin sampai tulang, ngilu yang membeku. Aku menggigil seperti digigit oleh dingin, membuat gigiku ingin bergemelutuk dan akan mengeluarkan uap es ketika aku berbicara dan bibirku kini menjadi kelu. Padahal badanku dibungkus jaket tebal bagai berbalut-balut. Aku seperti hendak meringkus diri pada kedua tanganku yang bersilang di atas dada.
Berbeda sekali dengan Daeng Tata yang santai saja menautkan kedua tangannya di belakang punggung karena sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Aku yakin telapak tangannya akan berkeringat dan kulitnya bakal meleleh lantaran peluh, tatkala nanti ia ke Makassar yang teriknya garang dengan niat mencari anaknya yang tak pernah menjenguknya beberapa tahun ini, semenjak pertengkaran yang aku pun tahu. Bagai menunaikan hajat ke tanah suci yang tak pernah terwujud karena uangnya tidak pernah cukup dan tiap tahun biayanya selalu naik.
Sungguh lelaki tua di sampingku ini seakan tidak bisa berpisah dari gunung Bawakaraeng yang ia jaga melebihi dari hidupnya. Ia menanam Mahoni dan jati serta pohon jenis lainnya di lereng bukit, dan di lokasi yang pohonnya terbabat di sekitar gunung. Bibitnya ia semai di pekarangan rumahnya. Sebab jasanya itu ia mendapatkan upah tiap bulan dari pemerintah Gowa yang tidak cukup buat makan berhari-hari. Lembaran uang itu ia tabung dalam kaleng biscuit entah berapa tahun, yang telah penuh. Namun jika dikumpulkan dan diikat dengan karet jumlahnya tak seberapa, tidak sebanding dengan jerih payahnya. Aku mengetahuinya sebab ia bermaksud menitipkan segepok uang itu beberapa hari yang lalu kepadaku buat Amiruddin, anaknya. Uang kuliah untuk temanku itu. Dulu memang anaknya adalah temanku tapi setelah aku tahu semuanya, dia bukan lagi temanku. Lebih dari itu. Aku bilang, Amiruddin memiliki usaha yang tidak tetap.
“Bunga, sampaikan salam saya pada Anakku yang masih keras hati. Bilang, saya sangat merindukannya,” ujarnya lembut nan tegas tanpa melepas pandang melihat kota Makassar yang berkilau gemilang serupa lampu senter yang benderang di tengah kegelapan, seperti kumpulan cahaya.
“Tata, tahu sendiri sikapnya yang tak mau dengar. Dan aku tidak bisa memaksa,” kataku setelah agak lama terdiam, lantaran aku sibuk menghalau dingin yang kian merayap pada hawa yang mulai senyap. Kulihat pelita di rumah penduduk di kaki dan di pinggang gunung sudah mulai berkeliaran bagai percikan sinar yang menyebar, bak kunang-kunang yang saling menjauh mencari tempat hinggap.
“Bujuk dia sampai mau. Katakan lagi padanya bahwa saya akan minta maaf, kalau perlu saya akan bersujud di kakinya. Akan kutinggalkan semua kebiasaan yang dimatanya adalah dosa. Hanya dia satu-satunya harapanku, Bunga. Harta warisan peninggalan almarhumah istriku yang ingin kususul di tanah suci. Dialah yang dapat mewujudkannya.” Kali ini ia menjenguk mukaku yang hampir beku, menatap asa begitu memelas.
“Iye, Tata, akan aku usahakan,” ucapku dengan gigi bergeretak. Kendati aku tidak tahu dimana Amiruddin sekarang. Namun aku yakin tidak susah untuk menemukannya. Sebab dia tidak kuliah lagi. Lebih memilih menyeru jalan agama ketimbang menuntut ilmu di fakultas yang katanya tidak dibawa ke akhirat.
***
“Aku belum menikah karena belum bisa melupakanmu. Dan aku akan terus menunggu sampai kamu mau, Maniah.” Sungai Jene Berang mengalir deras seperti meluap, menenggelamkan bongkahan batu kali yang terserak. Maniah bagai terseret oleh arusnya, telinganya berdengung mendengar ucapan Andi Baso. Pertemuan di tepi sungai di suatu pagi yang hendak beranjak, ketika Maniah usai membasuh diri dan membersihkan cucian.
“Saya sudah punya Daeng Tata!” jawab Maniah bergetar, agak terperangah. Meraba-raba kemauan hatinya.
“Itu bukan masalah jika kamu mau.”
Maniah menatap lelaki itu begitu lama seperti hendak menemukan keseriusan. Lelaki yang pernah ditolak sebab tak mampu memenuhi permintaan orangtuanya, sehingga Maniah mengubur cintanya dalam-dalam. Pertemuan itu rutin meski tidak setiap pagi dan kadang di tempat berbeda yang tidak diketahui orang lain, saat sepi. Sampai kesalahan itu diperbuat, yang membuat Daeng Tata senang karena tidak tahu.
“Kamu hamil, Maniah?”
Perempuan itu tidak mampu berterus terang karena didera dosa. Ia gelap mata. Andi Baso sangat sulit diabaikan. Bukan hanya karena ada hati, melainkan menjanjikan hidup layak dan nantinya bisa naik haji. Lelaki itu telah mapan. Kupingnya sudah terlalu panas mendengar segala gunjingan hina akan hidupnya yang tak kunjung membaik.
Maniah merasa tidak dipandang di tengah keluarga dan di setiap pesta yang dikunjunginya. Tidak diperbolehkan berjejer menyambut tamu di ruang depan karena belum haji. Cuma kerap mendapat tempat di dapur dan dianggap serupa asap yang mengepul lalu lenyap tak bersisa dan tak ada yang peduli. Hanya disuruh bantu-bantu memasak. Lantaran malu, ia tak tahan. Ketika kesempatan itu memberi peluang tak mungkin ia tampik kendati meninggalkan aib.
“Bayi itu anakku, Maniah.”
“Tidak Andi Baso. Daeng Tata sangat mengharapkannya. Saya akan menyusulmu nanti setelah saya melahirkan.”
***
Daeng Tata masih menatapku begitu teduh penuh pancaran kasih seperti menganggap aku adalah anaknya.
“Terima kasih, Bunga. Mari kita turun. Sepertinya kamu sudah tidak tahan dingin. Teman-temanmu juga sudah lama memanggil. Kamu tahu, Bunga? Kamu mirip istriku waktu muda.”
Aku tidak tersipu dengan gurauannya. Aku malah makin merasa bersalah. Ah, seandainya Daeng Tata tahu tentang rahasia yang kubawa, titipan pesan dari ibu yang mesti kusampaikan. Mengenai masa lalu yang tak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengatakan, istrimu belum mati dan Amiruddin bukan anakmu. Namun mulutku ini tak sampai hati mengutarakan maksud di setiap kesempatan berdua dengannya seperti tercekat di tenggerokan. Padahal besok aku sudah kembali ke Makassar.
Teman-temanku sudah membereskan segala peralatan camping tak terkecuali sisa-sisa berupa sampah. Memastikan tak ada yang ketinggalan, semuanya ada dalam ransel besar di pundak. Setelah berucap syukur, kami siap turun gunung. Di lembah Ramma, di rumah panggung Daeng Tata, kami akan istirahat. Barangkali sampai pagi meninggalkan hari. Semoga kesempatan terakhir itu tidak aku siasiakan untuk membuka mulut, atau tidak sama sekali.
***
Sinjai, 29 Oktober 2008
Catatan:
Gunung Bawakaraeng yang berarti Mulut Tuhan adalah tempat Syekh Yusuf berangkat ke Mekkah. Ulama sufi yang paling terkenal di seantero Sulawesi, dipercaya masyarakat bagai ditelan lalu hilang dan muncul di tanah suci. Dari sini awal mula ritual haji Bawakaraeng.
Daeng: Panggilan sayang untuk suami yang berarti kakak.
Anri: panggilan sayang untuk istri yang berarti adik.
Cerpen Emil Akbar
Dimuat di Majalah Gong Edisi: 111/X/2009
Seperti tawaf di Ka’bah, saat itu jamaah yang datang dari berbagai daerah, tengah khusyuk mengitari tugu beton yang pernah dibangun Belanda beberapa waktu silam, sambil mengumandangkan kalimat tauhid dengan tubuh bergoyang laksana ilalang yang menari ditiup angin. Ketika gerombolan itu datang menghujat.
“Syirik!”
“Bukan ajaran Islam.”
“Bubarkan!”
***
Aku selalu heran. Ibu sering melarangku pergi ke Malino untuk mengisi liburan semenjak masih SMA sampai sekarang, aku kuliah dan menjadi anak pencinta alam. Paling tidak ibu sering menghalang-halangi niatku dengan berbagai alasan. Padahal di sana aku punya warisan peninggalan ayah, berupa tempat penginapan yang dikelola orang lain. Makanya kerap kali aku berangkat diam-diam. Sepulang dari Malino, ibu pasti tahu dan langsung menghukum dengan cara mendiamkanku beberapa hari. Sejak itu aku tahu ibu tidak pernah ke sana.
Ketika ibu bertanya apa saja yang kulakukan setiap aku berkunjung ke sana, kulihat wajahnya harap-harap cemas seperti was-was yang tak semestinya. Bagai anak kecil yang ketahuan mencuri, kuceritakan semuanya termasuk pengalamanku mendaki puncak gunung Bawakaraeng dan kudapati di sana ada ritual haji. Ibu makin panik dan kian hari mengurung diri di dalam kamar. Saat kutanya kenapa? Ibu bungkam seribu bahasa seperti bertingkah yang tidak kumengerti. Tatkala kini berbaring lemah di rumah sakit, barulah ibu mau bercerita.
“Bunga, kamu punya seorang kakak.”
***
“Kapan kita naik haji, Daeng?” tanya Maniah yang sebenarnya tidak perlu Daeng Tata jawab sebab ia tahu istrinya itu hanya mengeluhkan nasib yang tak pernah bisa simpan uang.
“Sabarlah dulu, Anriku. Bila tiba waktunya, kita pasti akan ke tanah suci. Untuk itu kita jangan putus berdoa,” nasihatnya itu belum mampu meluluhkan hati Maniah yang punya mau.
“Percuma berdoa tanpa usaha, Daeng. Apa yang bisa diandalkan dari sepetak sawah warisan orangtuamu yang tak seberapa itu. Tak cukup bahkan untuk perut kita. Sayuran dan kadang padi yang kita tanam harganya selalu rendah, tidak pernah naik. Kita tinggal di hamparan gunung yang luas tapi milik kita tidak lebih dari secuil. Dan apa pula yang Daeng bisa lakukan selain bertani.”
Daeng Tata meredam amarah yang menghantam dada, berusaha maklum akan ucapan istrinya yang begitu tajam menusuk. Barangkali Maniah tidak sadar tengah menyinggungnya.
Dulu, orangtuanya memang punya banyak tanah. Namun tanah itu dijual murah karena didesak oleh usia mereka untuk naik ke tanah suci sebelum maut menjemput, dan beberapa tanah disita lantaran orangtuanya mengambil pinjaman untuk menambah upah naik haji, sebab uang hasil penjualan tanah belum juga cukup memenuhi ongkos. Juga buat selamatan sebelum dan sesudah naik haji. Harus dilunasi karena sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk membereskan segala hajat yang tertunggak. Beberapa kali Daeng Tata didatangi di dalam mimpi, orangtuanya mengemis memintanya segera membayar utang mereka kepada yang bersangkutan yang memang sering menagih. Padahal sisa tanah yang mereka wariskan adalah biaya hidup Daeng Tata sehari-hari.
Waktu itu, tanah memang seperti tidak ada harganya sebab jarang yang mau beli. Apalagi terletak di daerah puncak. Namun sekarang di tanah itu sudah banyak berdiri Vila, tempat penginapan untuk para pelancong yang berwisata ke Malino yang terkenal dengan air terjun dan udaranya yang sejuk.
“Besok saya akan ke atas, Anri. Kamu mau ikut?” bujuknya agak mengalihkan pembicaraan agar perasaan istrinya sedikit lunak, lantaran malam ini lelaki itu membutuhkannya. Ia memegang bahu istrinya pelan yang sedang berbaring membelakanginya.
“Tidak. Saya tidak percaya lagi, Daeng. Saya capek berangan-angan. Saya tidak mau pahala yang sama dengan naik ke Mekkah di atas gunung Bawakaraeng itu. Apakah Daeng tidak tahu? Banyak yang bilang ibadah ke sana itu keliru.” Maniah menolak secara halus, menggeser pundaknya biar terlepas dari tangan suaminya yang membelai bahunya.
“Ah, tahu apa mereka itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya hendak memaksakan ajaran yang katanya murni!” ujarnya seperti mengumpat. Menghempaskan diri karena merasa gagal melelehkan kebekuan istrinya.
Sungguh Daeng Tata sangat sulit menakhlukkan tabiat istrinya yang keras hati ketika sedang merajuk. Perempuan yang ia nikahi mati-matian sebab ia punya saingan. Ia rela menghabiskan tanah warisannya yang tersisa buat memenuhi permintaan calon mertuanya yang banyak ulah itu, sebab ada orang lain yang juga hendak melamar. Kepada pemberi yang tertinggi, mereka melepas anak gadisnya.
“Daeng, bagaimana kalau saya ke Makassar mencari kerja?” Tiba-tiba Maniah mengajukan usul yang tentu saja mengejutkan Daeng Tata. I strinya membalikkan badan menatapnya. Berkat pelita minyak yang menyala redup, ia bisa melihat mata istrinya yang berbinar, ada semangat di dalamnya.
“Seperti waktu gadis dulu. Saya akan bekerja sebagai buruh pabrik dan bakal menabung,” lanjutnya penuh harap, demikian riang seperti mengejar impian.
“Anri, kau akan lama di sana nantinya. Dengan begitu kau tega meninggalkan saya sendirian di sini.”
“Tidak apa, demi masa depan kita. Kelak bila sudah cukup uang dan pengalaman saya akan mengajakmu serta. Kita buka usaha di sana.”
“Tidak. Saya tidak mengijinkanmu!”
“Daeng, tenang saja. Sesekali saya akan menjengukmu.”
Suaminya bungkam yang bukan hanya diam. Maniah juga sejenak membisu sekedar mencari jawaban yang diinginkannya. Namun air muka Daeng Tata tidak berubah, dan istrinya itu sudah mengerti bahwa ia tidak bakal mendapatkan restu untuk pergi. Sambil kembali membalikkan badan, ia tetap menceracau. Tak mau menyerah.
“Kakak-kakakku sudah haji semua. Adik lelakiku yang pedagang itu sudah berangkat. Saya saja yang melarat seperti ini,” suaranya lirih menyindir. Namun ia tidak memperoleh tanggapan selain sunyi.
“Besok, naiklah ke atas supaya diberi gelar Haji Bawakaraeng. Teruslah seperti itu, sampai kapan pun, Daeng tidak akan mampu naik haji.”
Maniah diambang putus asa, memadamkan lampu minyak. Tidak peduli lagi dengan suaminya yang malam itu berhasrat bikin anak. Boleh jadi istrinya itu sering uring-uringan lantaran belum melahirkan buah hati. Pernah Daeng Tata dan maniah mendatangi sanro untuk berobat setelah lama menunggu. Namun dukun itu menyurutkan harapan. Katanya, Daeng Tata punya mani yang terlalu panas hingga mematikan indung telur. Lain hari berujar, rahim Maniah telah dingin dan beku. Terakhir menyimpulkan, mereka tidak cocok.
Daeng Tata tidak bisa tidur, memandang nanar gelap yang mengerubungi.
***
Dan Sekarang aku berada di sini untuk menemuinya.
Di atas gunung Bawakaraeng, angin menampar tubuh ringkih Daeng Tata yang tak goyah, memandang jauh di bawah sana. Bagai di laut, langit merendah begitu dekat sebab puncak bukit itu menjulang seperti hendak menjangkau cakrawala dengan gumpalan mega-mega berarak-arak serupa ombak yang tak surut, bergulung-gulung dengan pekatnya. Tampak megah keemasan pada senja yang bangkit, pertanda malam akan memeluk hari. Dan setiap kali awan itu melintas, bayangannya tampak berkejaran di permukaan bumi.
Deru angin terus menerpanerpa. Hembusan itu bertiup kencang membuat celana kain dan baju lusuh serta sarung yang tersampir di pundaknya berkibar-kibar ke belakang. Kopiah hitam bertengger di kepalanya yang beruban pun telah pudar serupa dirinya yang digerogoti usia.
Lelaki tua itu masih menatap, barangkali nun pada hamparan kota Makassar yang merajalela, tanah daratan yang jauh dari sini dan hidup dengan gemerlap, kelap-kelip yang mengalahkan kedap-kedip bintang yang mulai bermunculan di langit yang sebentar lagi menghitam, seperti perempuan nakal yang main mata.
Aku sejak tadi mengamatinya dari jarak yang tak dekat. Agak ke bawah, di balik hutan yang dihuni halimun, kabut asap tipis nan dingin yang lalu lalang. Aku melangkah mendekatinya dengan kaki kuseret biar berisik supaya ia berpaling, tapi Daeng Tata tetap bergeming hingga aku berada sejajar dengannya. Dingin kian merasuk mungkin sampai tulang, ngilu yang membeku. Aku menggigil seperti digigit oleh dingin, membuat gigiku ingin bergemelutuk dan akan mengeluarkan uap es ketika aku berbicara dan bibirku kini menjadi kelu. Padahal badanku dibungkus jaket tebal bagai berbalut-balut. Aku seperti hendak meringkus diri pada kedua tanganku yang bersilang di atas dada.
Berbeda sekali dengan Daeng Tata yang santai saja menautkan kedua tangannya di belakang punggung karena sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Aku yakin telapak tangannya akan berkeringat dan kulitnya bakal meleleh lantaran peluh, tatkala nanti ia ke Makassar yang teriknya garang dengan niat mencari anaknya yang tak pernah menjenguknya beberapa tahun ini, semenjak pertengkaran yang aku pun tahu. Bagai menunaikan hajat ke tanah suci yang tak pernah terwujud karena uangnya tidak pernah cukup dan tiap tahun biayanya selalu naik.
Sungguh lelaki tua di sampingku ini seakan tidak bisa berpisah dari gunung Bawakaraeng yang ia jaga melebihi dari hidupnya. Ia menanam Mahoni dan jati serta pohon jenis lainnya di lereng bukit, dan di lokasi yang pohonnya terbabat di sekitar gunung. Bibitnya ia semai di pekarangan rumahnya. Sebab jasanya itu ia mendapatkan upah tiap bulan dari pemerintah Gowa yang tidak cukup buat makan berhari-hari. Lembaran uang itu ia tabung dalam kaleng biscuit entah berapa tahun, yang telah penuh. Namun jika dikumpulkan dan diikat dengan karet jumlahnya tak seberapa, tidak sebanding dengan jerih payahnya. Aku mengetahuinya sebab ia bermaksud menitipkan segepok uang itu beberapa hari yang lalu kepadaku buat Amiruddin, anaknya. Uang kuliah untuk temanku itu. Dulu memang anaknya adalah temanku tapi setelah aku tahu semuanya, dia bukan lagi temanku. Lebih dari itu. Aku bilang, Amiruddin memiliki usaha yang tidak tetap.
“Bunga, sampaikan salam saya pada Anakku yang masih keras hati. Bilang, saya sangat merindukannya,” ujarnya lembut nan tegas tanpa melepas pandang melihat kota Makassar yang berkilau gemilang serupa lampu senter yang benderang di tengah kegelapan, seperti kumpulan cahaya.
“Tata, tahu sendiri sikapnya yang tak mau dengar. Dan aku tidak bisa memaksa,” kataku setelah agak lama terdiam, lantaran aku sibuk menghalau dingin yang kian merayap pada hawa yang mulai senyap. Kulihat pelita di rumah penduduk di kaki dan di pinggang gunung sudah mulai berkeliaran bagai percikan sinar yang menyebar, bak kunang-kunang yang saling menjauh mencari tempat hinggap.
“Bujuk dia sampai mau. Katakan lagi padanya bahwa saya akan minta maaf, kalau perlu saya akan bersujud di kakinya. Akan kutinggalkan semua kebiasaan yang dimatanya adalah dosa. Hanya dia satu-satunya harapanku, Bunga. Harta warisan peninggalan almarhumah istriku yang ingin kususul di tanah suci. Dialah yang dapat mewujudkannya.” Kali ini ia menjenguk mukaku yang hampir beku, menatap asa begitu memelas.
“Iye, Tata, akan aku usahakan,” ucapku dengan gigi bergeretak. Kendati aku tidak tahu dimana Amiruddin sekarang. Namun aku yakin tidak susah untuk menemukannya. Sebab dia tidak kuliah lagi. Lebih memilih menyeru jalan agama ketimbang menuntut ilmu di fakultas yang katanya tidak dibawa ke akhirat.
***
“Aku belum menikah karena belum bisa melupakanmu. Dan aku akan terus menunggu sampai kamu mau, Maniah.” Sungai Jene Berang mengalir deras seperti meluap, menenggelamkan bongkahan batu kali yang terserak. Maniah bagai terseret oleh arusnya, telinganya berdengung mendengar ucapan Andi Baso. Pertemuan di tepi sungai di suatu pagi yang hendak beranjak, ketika Maniah usai membasuh diri dan membersihkan cucian.
“Saya sudah punya Daeng Tata!” jawab Maniah bergetar, agak terperangah. Meraba-raba kemauan hatinya.
“Itu bukan masalah jika kamu mau.”
Maniah menatap lelaki itu begitu lama seperti hendak menemukan keseriusan. Lelaki yang pernah ditolak sebab tak mampu memenuhi permintaan orangtuanya, sehingga Maniah mengubur cintanya dalam-dalam. Pertemuan itu rutin meski tidak setiap pagi dan kadang di tempat berbeda yang tidak diketahui orang lain, saat sepi. Sampai kesalahan itu diperbuat, yang membuat Daeng Tata senang karena tidak tahu.
“Kamu hamil, Maniah?”
Perempuan itu tidak mampu berterus terang karena didera dosa. Ia gelap mata. Andi Baso sangat sulit diabaikan. Bukan hanya karena ada hati, melainkan menjanjikan hidup layak dan nantinya bisa naik haji. Lelaki itu telah mapan. Kupingnya sudah terlalu panas mendengar segala gunjingan hina akan hidupnya yang tak kunjung membaik.
Maniah merasa tidak dipandang di tengah keluarga dan di setiap pesta yang dikunjunginya. Tidak diperbolehkan berjejer menyambut tamu di ruang depan karena belum haji. Cuma kerap mendapat tempat di dapur dan dianggap serupa asap yang mengepul lalu lenyap tak bersisa dan tak ada yang peduli. Hanya disuruh bantu-bantu memasak. Lantaran malu, ia tak tahan. Ketika kesempatan itu memberi peluang tak mungkin ia tampik kendati meninggalkan aib.
“Bayi itu anakku, Maniah.”
“Tidak Andi Baso. Daeng Tata sangat mengharapkannya. Saya akan menyusulmu nanti setelah saya melahirkan.”
***
Daeng Tata masih menatapku begitu teduh penuh pancaran kasih seperti menganggap aku adalah anaknya.
“Terima kasih, Bunga. Mari kita turun. Sepertinya kamu sudah tidak tahan dingin. Teman-temanmu juga sudah lama memanggil. Kamu tahu, Bunga? Kamu mirip istriku waktu muda.”
Aku tidak tersipu dengan gurauannya. Aku malah makin merasa bersalah. Ah, seandainya Daeng Tata tahu tentang rahasia yang kubawa, titipan pesan dari ibu yang mesti kusampaikan. Mengenai masa lalu yang tak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengatakan, istrimu belum mati dan Amiruddin bukan anakmu. Namun mulutku ini tak sampai hati mengutarakan maksud di setiap kesempatan berdua dengannya seperti tercekat di tenggerokan. Padahal besok aku sudah kembali ke Makassar.
Teman-temanku sudah membereskan segala peralatan camping tak terkecuali sisa-sisa berupa sampah. Memastikan tak ada yang ketinggalan, semuanya ada dalam ransel besar di pundak. Setelah berucap syukur, kami siap turun gunung. Di lembah Ramma, di rumah panggung Daeng Tata, kami akan istirahat. Barangkali sampai pagi meninggalkan hari. Semoga kesempatan terakhir itu tidak aku siasiakan untuk membuka mulut, atau tidak sama sekali.
***
Sinjai, 29 Oktober 2008
Catatan:
Gunung Bawakaraeng yang berarti Mulut Tuhan adalah tempat Syekh Yusuf berangkat ke Mekkah. Ulama sufi yang paling terkenal di seantero Sulawesi, dipercaya masyarakat bagai ditelan lalu hilang dan muncul di tanah suci. Dari sini awal mula ritual haji Bawakaraeng.
Daeng: Panggilan sayang untuk suami yang berarti kakak.
Anri: panggilan sayang untuk istri yang berarti adik.
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



















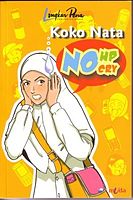
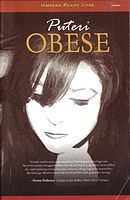
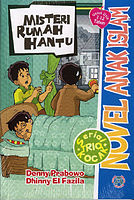


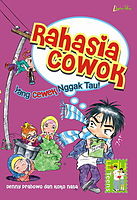


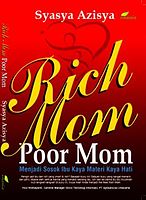



0 komentar:
Posting Komentar